Awas, Peraturan Presiden No 78 Bisa Hapus Hak Dasar atas Tanah
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Agraria
Selasa, 09 Januari 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, menuai tanggapan negatif. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menganggap beleid tersebut harus diwaspadai, sebab di dalamnya merancang tata-cara pemerintah menghapus hak-hak dasar rakyat atas tanah.
Dalam pernyataan resminya pekan lalu, KPA mengatakan, hadirnya Perpres ini menunjukkan bahwa hak atas tanah (HAT) sebagai konstitusionalitas petani, buruh tani, masyarakat adat dan rakyat miskin yang termarginalkan dalam struktur agraria, termasuk janji penyelesaian konflik agraria dalam kerangka Reforma Agraria semakin jauh panggang dari api.
KPA membeberkan 6 pandangannya terhadap substansi Perpres No. 78 Tahun 2023 itu. Yang pertama, KPA menyebut penerbitan Perpres ini merupakan pembohongan produk hukum. Sebab di balik judulnya yang terkesan humanis, Perpres ini berorientasi sebaliknya, yakni bertujuan untuk menghapus hak dasar rakyat atas tanah yang telah dijamin Konstitusi dan UUPA 1960.
"Nama Perpres ini memang terkesan humanis karena hendak mengurus “dampak sosial kemasyarakatan” sebagai akibat dari kebutuhan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Ironisnya, isinya merumuskan bagaimana tata cara pemerintah menggusur masyarakat dari tanah yang menjadi tempat tinggal, tanah kelahiran dan sumber penghidupannya," kata Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, pada 4 Januari 2024.

Dewi mengatakan, semakin ironis karena nilai-nilai philosofis dan ideologis dari konstitusionalisme agraria warga yang telah dilindungi dan dijamin Konstitusi dan UUPA berujung pada pemberian santunan. Pasal 1 Ayat (3) Perpres berbunyi “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.”
Pemberian santunan, kata Dewi, memberi kesan sebagai bentuk sumbangan kemanusiaan agar masyarakat bersedia digusur. Padahal, istilah santunan dipakai karena hak masyarakat atas tanah dianggap telah nyata-nyata bukan milik rakyat, kemudian masyarakat diusir dengan menggunakan istilah pemberian santunan.
"Itulah sebabnya Perpres 78 tidak menggunakan terminologi ganti-kerugian seperti UU Pengadaan Tanah. Perpres ini menggunakan istilah lain yaitu “santunan”, yang menunjukkan bahwa hak atas tanah warga tidak ada, tidak diakui, maka pemerintah melakukan bentuk kebaikan atau kemurahan hati (charity) pemerintah dengan memberikan santunan," katanya.
Dalam terminologi santunan Perpres No. 78 Tahun 2023, lanjut Dewi, tidak ada persfektif kewajiban negara (state obligation) untuk membayar ganti-kerugian yang diderita masyarakat atas kehilangan tanahnya secara patut dan proporsional dengan memperhitungkan kerugian materil maupun non-materil, sehingga tetap bermartabat pasca dihilangkan hak atas tanahnya.
Yang kedua, KPA memandang Perpres No. 78 Tahun 2023 memfasilitasi model pembangunan pro-modal besar yang selama ini dijalankan. Perpres ini, menurut Dewi, merancang sistem pengalokasian tanah yang semakin berwatak pro-pemodal melalui mantra-mantra "demi pembangunan”, ketimbang berwatak kerakyatan (populis) melalui pembangunan yang bersperpektif Reforma Agraria.
"Padahal, sejak 1960 melalui UUPA para pendiri bangsa sudah sangat revolusioner dan visioner dalam merumuskan fondasi hukum agraria yang kuat dan populis, yakni mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong," kata Dewi.
Perspektif pemberian santunan dan charity uang kepada masyarakat korban, lanjut Dewi, yang menguasai dan memiliki tanah merupakan perspektif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUPA. Alih-alih memperbaiki kelemahan-kelemahan regulasi dan birokrasi yang menghambat penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, pengakuan hak atas tanah bagi rakyat, justru presiden melahirkan perpres yang semakin memadamkan bahkan mengancam kebijakan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar yang telah dijanjikan oleh presiden sendiri. Dengan demikian, watak politik-hukum agraria yang dianut Perpres No. 78 Tahun 2023 menyimpang dari ideologi UUPA.
Yang ketiga, KPA menilai Perpres ini bersifat anti-Reforma Agraria dan menyeleweng jauh dari prinsip hukum agraria nasional dengan klaim “pemerintah pemilik tanah”. Dengan prinsip semacam itu sudah barang tentu diskriminasi hak petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin serta kelompok marginal lainnya yang masih memperjuangkan hak atas tanah akan semakin meluas, konflik agraria akan semakin parah.
"Perpres ini patut ditolak sebab menganut paham yang sesat bahwa tanah-tanah yang dikuasai masyarakat adalah bersumber dari “tanah milik” pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan tanah negara dalam pengelolaan pemerintah alias hak pengelolaan (HPL) (Pasal 3)," ujar Dewi.
Dewi melanjutkan, Pasal 3 di atas adalah bentuk nyata praktik domien-verklaring seperti jaman Belanda, yang telah dihapus UUPA. Selain itu, frasa “tanah milik pemerintah” dan “tanah negara dalam pengelolaan pemerintah” adalah bentuk kesewenang-wenangan lainnya yang ditentang UUPA, sekaligus melanggar Konstitusi. Pemerintah lupa, bahwa dalam hukum agraria nasional yang kita anut, pemerintah bukan lah pemilik tanah. Putusan MK terkait hak menguasai dari negara telah jelas menyatakan itu.
Perumus Perpres ini, imbuh Dewi, melanggar Pasal 9 UUPA yang telah menjamin bahwa tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Perpres ini, Dewi melanjutkan, memaknai konsep “masyarakat yang menguasai tanah” dengan sangat sempit dan legalistik semata. Akibatnya perspektif Perpres ini memandang masyarakat sebagai kelompok warga negara yang pada dirinya sama sekali tidak melekat hak atas tanah sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara melalui penguasa. Masyarakat menjadi kelompok ilegal dalam Perpres ini.
"Tidaklah mengherangkan jika bentuk penyelesaiannya adalah memberikan santunan, bukan dalam perspektif penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemulihan hak atas tanah masyarakat," ucapnya.
Keempat, selain penguasaan tanah oleh masyarakat tidak diakui, KPA melihat Perpres ini merumuskan prasyarat berlapis, yang diskriminatif dan berwatak ’pelit’ kepada rakyat, dengan cara menyaring siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan santunan.
Dewi menguraikan, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat (santunan) dari penanganan dampak sosial kemasyarakatan ini hanya bagi mereka yang menurut kaca-mata pemerintah telah menguasai dan memanfaatkan tanah (bukan miliknya) secara fisik paling singkat 10 tahun secara terus menerus.
Filter ke dua adalah syarat masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.
"Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Terkandung watak ‘pelit’ negara kepada rakyat terkait hak atas tanah, kontras dengan watak memanjakan investor melalui pemberian puluhan juta hektar tanah-tanah maha luas dalam bentuk HGU, HTI, HPL, izin tambang, dan lain-lain, kepada segelintir badan usaha," ujar Dewi.
Dengan rumusan pasal demikian, Dewi kemudian mempertanyakan bagaimana dengan wilayah-wilayah konflik agraria dimana petani dan masyarakat adat mengalami konflik dengan klaim-klaim HGU negara (BUMN/PTPN), HGU swasta, Perhutani, HTI, klaim kawasan hutan dan lain-lain. Dengan syarat-syarat penyaringan di atas, maka Perpres ini akan berlaku sangat diskriminatif terhadap perkampungan/desa-desa, tanah pertanian, wilayah adat dan daerah-daerah konflik agraria.
"Menurut normatif hukum dari Perpres ini, maka akan ada puluhan juta keluarga, petani, buruh, masyarakat adat dan kelompok rentan yang dianggap tidak berhak atas tanah, tidak layak juga mendapatkan santunan, sehingga satu-satunya opsi layak digusur langsung," katanya.
Kelima, KPA menganggap Perpres ini produk hukum yang tidak dibutuhkan, bentuk penghamburan uang Negara, memperparah carut-marut hukum, overlapped dan inkonsistensi dengan UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dewi menjelaskan Perpres No. 78 Tahun 2023 tidak perlu dan overlapped, sebab kebutuhan pemerintah untuk memperoleh tanah demi pembangunan dan investor sebenarnya dapat menggunakan instrumen UU Pengadaan Tanah dan regulasi turunannya. Diketahui bahwa UU pengadaan tanah telah diubah (diperkuat) pasal-pasalnya untuk kepentingan investasi dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Kemudian ”direvisi” lagi melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/ 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
Dewi bilang, UUCK telah memperluas cakupan “kepentingan umum” dalam UU Pengadaan Tanah tidak hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pengadaan tanah untuk kepentingan kawasan industri hulu dan hilir, minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan dan kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD.
Dalam Perpres ini, Dewi melanjutkan, pemerintah juga menunjukkan inkonsistensinya dengan cara menggunakan istilah “penyediaan tanah”, seolah berbeda dengan istilah “pengadaan tanah” dalam UU Pengadaan Tanah. Padahal Perpres ini menyatakan sendiri bahwa Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 1 Ayat (2)).
"Artinya Perpres ini mengatur hal yang sama dengan regulasi lainnya dengan menggunakan istilah berbeda-beda. Lantas, mengapa membuat regulasi baru? Sebuah penghamburan anggaran untuk urusan penyediaan tanah yang sudah ada instrumen hukumnya, lebih-lebih makin melahirkan carut-marut hukum agraria," katanya.
Keenam, KPA melihat wilayah berlaku Perpres ini dirancang secara nasional untuk percepatan proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan tanah dalam skala luas, meski demikian substansinya juga memuat tiga strategy exit kebutuhan khusus pemerintah untuk melanjutkan eksekusi pembangunan Proyek Rempang Ecocity-Batam.
Tiga strategy exit tersebut, kata Dewi, tampak ketika Perpres ini mengatur siapa leading sector birokrasi yang akan menjalankan mandat Perpres. Awalnya Perpres ini memberikan kewenangan kepada gubernur untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, disingkat Tim Terpadu (Pasal 8). Selanjutnya soal kewenangan Perpres ini mengatur sedemikian rupa agar pasal-pasalnya sesuai dengan kebutuhan spesifik eksekusi PSN Rempang.
"KPA memandang telah terjadi kemunduran drastis kualitas produk-produk hukum agraria di Indonesia yang menyangkut pertanahan, kehutanan, pertambangan, pertanian dan pangan. Atas dasar 6 pandangan di atas, maka KPA menyatakan menolak Perpres No. 78 Tahun 2023, mendesak Presiden RI untuk segera mencabut Perpres No. 78 Tahun 2023, dan mendesak pemerintah kembali pada Pasal 5 Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita UUPA 1960," kata Dewi.
"Kami juga mengecam DPR RI yang tidak menjalankan fungsi kontrolnya sebagai wakil rakyat. Seharusnya DPR RI menjadi terdepan dalam menegakkan konstitusi dengan cara memastikan seluruh tanah dan kekayaan alam bangsa ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah bukan dimiliki pemerintah sebagai kekuasaan absolut, dan tidak untuk diobral kepada segelintir kelompok badan usaha/korporasi dan pengusaha," imbuhnya.
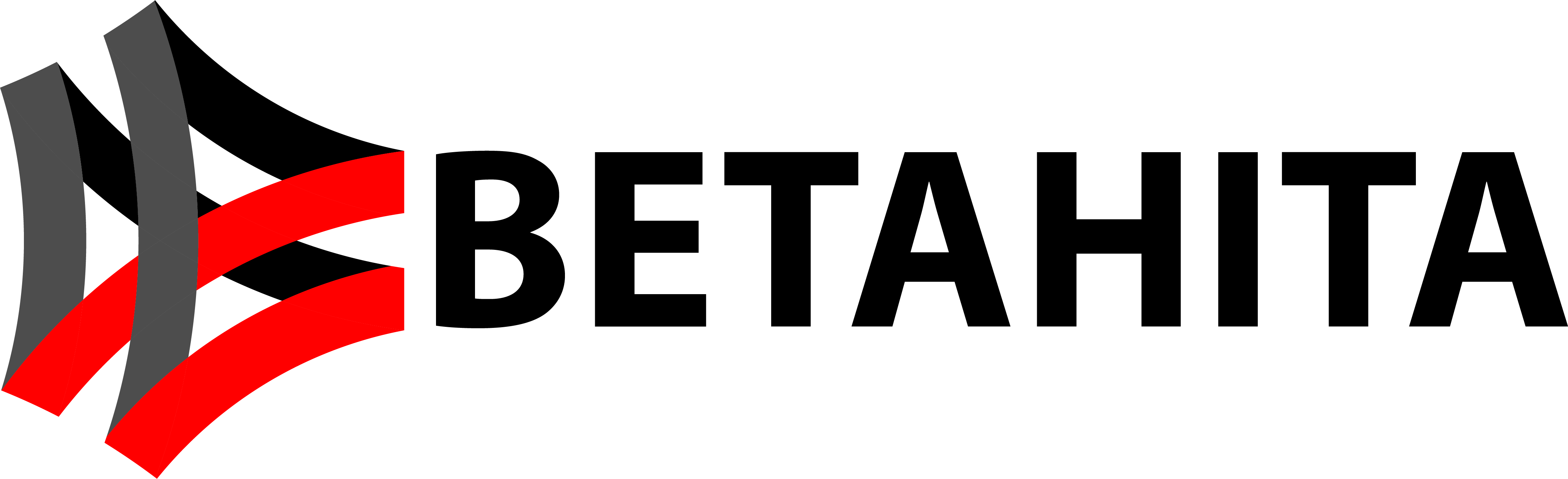


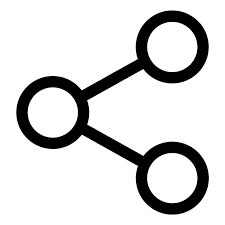 Share
Share

