Penertiban Izin Tumpul Pasca Bencana Sumatra
Penulis : Aryo Bhawono
Ekologi
Senin, 19 Januari 2026
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Rehabilitasi hutan, pencabutan atau pengurangan izin konsesi, hingga penegakan hukum pasca bencana Sumatera masih nihil dari agenda pemerintah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) beranggapan pemulihan mendasar dan jangka panjang atas bencana Sumatera masih dikesampingkan pemerintah.
Lima puluh hari pascabencana ekologis di Sumatra, belum tampak pemulihan bermakna maupun penegakan hukum. Bencana yang semula bersifat lingkungan kini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan, ditandai oleh hilangnya hak kebutuhan dasar. Aktivitas ekonomi lumpuh, gagal panen meluas, akses jalan terputus, listrik padam, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam.
Bahkan di Aceh, bencana ini turut menggerus kearifan lokal seperti tradisi Meugang, sebuah sistem solidaritas pangan rakyat yang hilangnya menandai runtuhnya tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini bertumpu pada keseimbangan ekologis.
Koordinator Desk Disaster WALHI region Sumatra, Wahdan, menyampaikan minimnya sarana evakuasi, lambannya respons, serta wacana relokasi tanpa partisipasi warga memperparah penderitaan masyarakat. Ironisnya, di tengah krisis kemanusiaan, negara justru sigap memobilisasi puluhan alat berat untuk memindahkan kayu-kayu gelondongan pascabanjir dengan tanpa transparansi dan akuntabilitas.

“Fakta ini memperlihatkan keberpihakan yang timpang: absen saat rakyat menyelamatkan nyawa, hadir saat berhadapan dengan sumber daya bernilai ekonomi,” katanya dalam diskusi pada Jumat (16/1/2026).
Posisi geografis Aceh strategis sekaligus rentan. Daerah ini berada di pertemuan lempeng tektonik aktif dan memiliki bentang alam yang kaya seperti hutan, sungai, pesisir, dan laut sehingga pengelolaannya membutuhkan kehati-hatian ekologis. Namun dalam dua dekade pasca tsunami 2004, tekanan terhadap lingkungan justru semakin meningkat akibat ekspansi industri ekstraktif.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi, Aceh, Afifuddin, menyebutkan pemulihan kawasan terdampak bencana di Aceh tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan selama ini. Pencabutan izin ekstraktif di wilayah-wilayah rentan dan memulihkan fungsi ekologisnya seperti sediakala adalah keputusan yang tidak bisa ditawar lagi.
“Masyarakat Aceh itu paham atas kerentanan ruang hidupnya, makanya mereka menjaga wilayah fungsi khusus dengan pengetahuan tradisional yang terbukti secara turun temurun melalui tradisi. Harusnya pengetahuan tradisional ini menjadi acuan negara untuk melakukan mitigasi dan dimuat menjadi peta rawan bencana bersifat partisipatif,” ucapnya.
Bencana ekologis di Aceh Tamiang dan Aceh Timur harus menjadi momentum bagi negara untuk keluar dari fase impunitas, menegakkan hukum lingkungan secara tegas, dan berpihak pada kehidupan dan keadilan ekologis. Jika akar persoalan ini tidak disentuh serta kebijakan tidak berpihak pada rakyat dan kelestarian lingkungan, bencana akan terus berulang dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sedangkan di Sumatera Utara, terutama ekosistem Batang Toru yang menjadi lokus bencana, merupakan kawasan dengan morfologi pegunungan yang terbentuk akibat sesar besar dan memiliki jaringan sungai yang mengalir dari wilayah hulu menuju lembah cekungan dan kawasan hilir. Kondisi geomorfologi ini menjadikan Batang Toru sangat bergantung pada tutupan hutan sebagai penyangga hidrologis alami. Ketika tutupan vegetasi hutan berkurang, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis, sementara aliran permukaan (run-off) meningkat tajam dan langsung mengalir ke wilayah hilir.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik, menyebutkan saat ini seluas 10.795 hektare hutan di Batang Toru telah dialihfungsikan dalam sepuluh tahun terakhir. Perkiraannya sekitar 5,4 juta pohon hilang akibat aktivitas tujuh perusahaan besar di kawasan tersebut.
Deforestasi di Batang Toru ini dilegalisasi melalui perizinan. Aktivitas tersebut juga telah memutus koridor satwa liar serta merusak alur sungai yang sejatinya berfungsi sebagai penyangga ekologis dan perlindungan alami dari bencana.
Menurutnya negara tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Kasus Batang Toru pun menjadi cermin bagaimana pembangunan yang mengabaikan mitigasi ekologis, melalui proyek PLTA, pertambangan, dan konversi hutan menjadi perkebunan telah menggerus tutupan hutan dan melemahkan kemampuan alam menyerap air serta meredam kejadian ekstrem.
Tanpa kebijakan perlindungan hutan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perusakan lingkungan, bencana ekologis serupa akan terus berulang dengan dampak yang semakin luas dan berat,” ucapnya.
Sementara proses pemulihan khususnya terkait rencana pemerintah untuk menyediakan hunian tetap bagi para korban bencana jangan sampai menimbulkan masalah baru. Pemerintah harus menjamin tidak ada sengketa hak atas tanah di atas lahan yang hendak dibangun hunian tetap. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa distribusi hunian tetap harus adil untuk seluruh masyarakat dan tidak ada yang dirugikan atas kebijakan tersebut.
Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian beranggapan penegakan hukum secara tegas harus dilakukan terhadap korporasi yang terbukti merusak lingkungan dan berkontribusi pada terjadinya banjir. Penegakan hukum ini meliputi sanksi pidana, perdata, dan administratif yang menimbulkan efek jera sekaligus mewajibkan pemulihan ekologis.
Menurutnya penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat atau pembangunan infrastruktur teknis, tetapi harus disertai upaya pemulihan mendasar dan jangka panjang.
“Ini termasuk rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, pencabutan atau pengurangan izin dari konsesi yang layak milik perusahaan, lalu didistribusikan kepada masyarakat korban bencana yang wilayahnya tidak mungkin lagi ditempati. Jika berhasil, maka cara ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya,” kata dia.
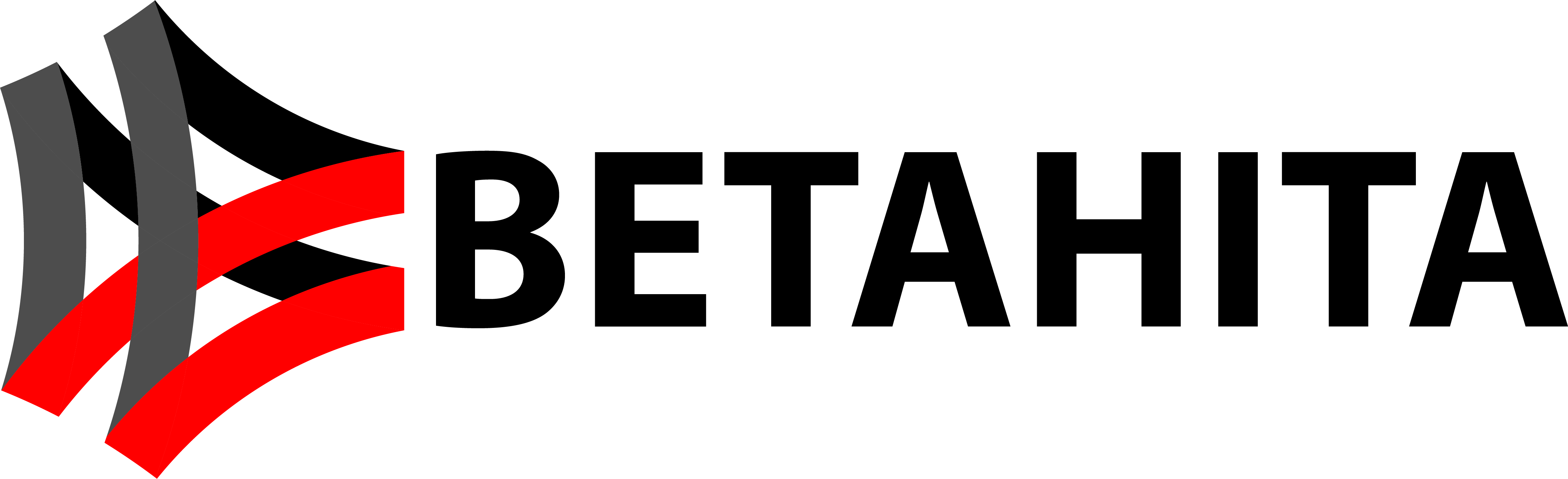


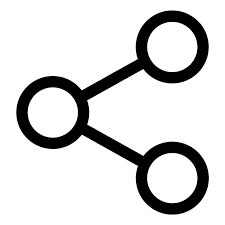 Share
Share

