KPA Ajari Anggota DPR dari Golkar Soal Reforma Agraria
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Agraria
Selasa, 09 Desember 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyayangkan dan mengecam pernyataan salah satu anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo, yang menuduh reforma agraria sebagai penyebab rusaknya hutan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Menurut KPA, yang terjadi malah sebaliknya, tragedi ekologis di Sumatera justru terjadi karena reforma agraria yang sejati dan sesuai mandat konstitusi tidak kunjung dijalankan.
“Apa hubungan reforma agraria dengan bencana yang terjadi? Menyalahkan reforma agraria, padahal reforma agraria yang sesuai dengan mandat konstitusi, Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA serta UUPA 1960 belum dijalankan secara genuine di Sumatera,” kata Dewi Kartika, Sekjen KPA, dalam sebuah keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).
Dewi mengatakan, ketimbang menyalahkan kebijakan pro-rakyat, seharusnya DPR secara gentle dan cerdas “menunjuk hidung” kebijakan pemerintah, termasuk berbagai produk UU yang pro-konsesi besar, dan telah memberi karpet merah pada praktik monopoli, deforestasi dan perusakan tanah-SDA oleh korporasi yang menjadi penyebab kerusakan hutan dan bencana.
“Kami tegaskan, pernyataan di atas sangat keliru, dapat menyesatkan publik, dan bisa mempermalukan diri sendiri di tengah berbagai negara hingga PBB telah memiliki komitmen kuat dan keberpihakan yang jelas kepada petani dan kaum marginal melalui kebijakan reforma agraria. Presiden Prabowo pun memiliki kebijakan reforma agraria,” kata Dewi.

Dewi mengatakan, pernyataan kontraproduktif semacam itu, justru menunjukkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman anggota DPR RI yang sangat miskin literasi mengenai masalah struktural agraria dan krisis lingkungan, tidak memahami apa reforma agraria. Lebih-lebih, secara tidak langsung telah menuduh rakyat dan kelompok marjinal (petani dan masyarakat adat) yang berhak atas reforma agraria sebagai biang keladi dari bencana.
Menurut Dewi, DPR RI seharusnya juga menyadari bahwa sumber dari segala sumber kesalahan dan akar masalahnya ada di tangan legislatif dan eksekutif. DPR sebagai pembuat UU justru yang selama ini telah memberikan keistimewaan secara membabi-buta dan terus memfasilitasi badan-badan usaha skala besar untuk melakukan deforestasi, tukar-guling kawasan dan penerbitan-perpanjangan-pembaruan konsesi (hak dan izin; HTI, HGU, IUP, Ijin lokasi, HPL) untuk bisnis kayu, sawit, tambang serta pengadaan tanah untuk PSN, KEK, KSPN, IKN, real estate, food estate dan sebagainya.
Saat ini, imbuh Dewi, puluhan juta hektare tanah, hutan dan kekayaan alam Indonesia dijarah dan dirusak oleh korporasi dan elit politik. Akibatnya 58 persen tanah di Indonesia dimonopoli oleh segelintir kelompok (konglomerasi/korporasi) yang menyebabkan Indonesia tenggelam dalam ketimpangan struktur agraria, ketidakadilan sosial dan kemiskinan hingga hilangnya daya dukung alam yang berujung pada banjir dan longsor di banyak tempat.
“Selanjutnya soal pernyataan tentang moratorium konsesi. Komisi IV DPR RI dan Partai Golkar seharusnya betul-betul mendengarkan aspirasi rakyat selama ini,” kata Dewi.
Dewi bilang, tuntutan menghentikan izin/hak konsesi bukan hal yang baru bagi rakyat, sebab sudah ratusan kali disuarakan rakyat. Namun seperti biasa, orientasi ekonomi-politik yang makin liberal dan kuat disetir pemodal telah membuat DPR dan pemerintah selalu mengabaikan tuntutan tersebut, justru semakin melegitimasi penerbitan konsesi perampas tanah dan perusak hutan.
Dewi mengatakan, Komisi IV DPR RI, termasuk Firman Subagyo harusnya mengingat kembali aspirasi rakyat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan DPR, Komisi IV dengan KPA pada Hari Tani Nasional, 24 September 2025 di Gedung DPR. Pada RDP tersebut KPA telah menyampaikan 9 tuntutan perbaikan atas masalah struktural terkait agraria-SDA, salah satunya adalah tuntutan moratorium konsesi.
Lebih jelas, KPA menuntut agar Presiden segera membekukan Bank Tanah, dan menghentikan penerbitan izin dan hak konsesi (moratorium) perkebunan, kehutanan, tambang (HGU, HPL, HGB, HTI, ijin lokasi, IUP), dan proses pengadaan tanah bagi PSN, KEK, Bank Tanah, Food Estate, KSPN dan IKN yang menyebabkan ribuan konflik agraria, penggusuran dan kerusakan alam. Selanjutnya, konsesi dan proyek pengadaan tanah yang tumpang tindih dengan tanah rakyat segera dikembalikan dalam kerangka reforma agraria.
Rapat ini selain dihadiri langsung oleh Pimpinan DPR dan Ketua Komisi IV DPR RI, juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN RI dan menteri lainnya. Pimpinan DPR, Ketua Komisi IV dan para menteri yang hadir membenarkan adanya situasi krisis, data dan fakta konflik agraria yang telah disampaikan masyarakat pada RDP tersebut. Bahkan diperoleh kesepakatan untuk melakukan perbaikan agar reforma agraria segera dijalankan.
“Oleh karena itu, menjadikan reforma agraria sebagai kambing hitam tidak hanya keliru besar, tetapi juga mengaburkan masalah utama yang harus diatasi bersama,” ucap Dewi.
Lebih lanjut Dewi menguraikan, klaim selanjutnya dari Firman Subagyo, bahwa kehancuran hutan di Sumatra dimulai sejak Era Reformasi tidaklah tepat. Sebab kehancuran itu telah muncul pula sejak Orde Baru. Salah satunya adalah pemberian konsesi kehutanan pada tahun 1984 berupa kepada PT Indorayon (sekarang PT Toba Pulp Lestari/TPL) milik Sukanto Tanoto seluas 150 ribu hektare (SK 203/kpts-IV/84).
Luas izin perusahaan itu bahkan sempat bertambah luasannya menjadi 180 ribu hektare saat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan. Lalu pada masa Menteri LHK Siti Nurbaya luasannya menjadi 168 ribu hektare sampai sekarang. Parahnya sejak 1984 sampai dengan saat ini, konsesi TPL telah merusak hutan hingga mencapai 269 ribu hektare. Konsesi HTI ini membentang di 12 kabupaten/kota, menjadikan TPL sebagai pemilik konsesi kehutanan terluas di Sumatera Utara.
Dewi mengungkapkan, telah berpuluh tahun masyarakat adat Tano Batak dan masyarakat sekitar Danau Toba menuntut agar operasi TPL ditutup, sebab konsesi tersebut telah merampas wilayah adat dan mengakibatkan berbagai bencana banjir, longsor dan pencemaran. Namun, seperti biasa pemerintahan lintas rezim dari masa Orde Baru hingga Reformasi sekarang ini tidak kunjung memenuhi aspirasi rakyat untuk menutup TPL.
“Kebijakan reforma agraria yang dituduh menjadi biang keladi kerusakan hutan justru merupakan jalan untuk mengatasi akar masalah tersebut. Sebab reforma agraria bertujuan untuk menertibkan konsesi dan menata ulang penguasaan tanah serta tata kelola agraria-SDA yang selama puluhan tahun tidak terkendali dan menyebabkan konflik agraria dari Aceh hingga Papua,” kata Dewi.
Penguasaan tanah di Indonesia alami ketimpangan akut
 Upaya pencarian korban hilang dan pembukaan akses jalan menggunakan alat berat di Agam. Foto: BNPB.
Upaya pencarian korban hilang dan pembukaan akses jalan menggunakan alat berat di Agam. Foto: BNPB.
Saat ini, sambung Dewi, Indonesia mengalami ketimpangan penguasaan tanah yang semakin akut. Di sektor industri kehutanan, 535 korporasi menguasai tanah seluas 34,18 juta hektare, 2.285 korporasi perkebunan sawit menguasai 17,3 hektare, lalu 9,1 juta hektare tanah dikuasai dan dieksploitasi oleh 959 korporasi tambang. Tidak sampai di situ, pemerintah terus menargetkan pembukaan hutan, merampas wilayah adat, desa dan tanah pertanian rakyat seluas 3,13 juta hektare untuk proyek food estate.
“Monopoli semacam inilah yang membuat hancurnya tanah dan ekosistem hutan di Indonesia akibat praktik perkebunan monokultur, eksploitasi tambang dan bisnis kehutanan yang tidak bertanggung jawab. Ini lah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria,” katanya.
Lebih jauh Dewi menjelaskan, tidak dijalankannya reforma agraria telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin masif, termasuk deforestasi, laju konversi tanah yang tidak terkendali, ketimpangan struktur agraria akibat monopoli tanah oleh sekelompok korporasi yang tidak bertanggung jawab. Bahkan banyak korporasi yang mengantongi izin dan hak secara ilegal dan membahayakan masyarakat serta lingkungan.
“Bencana yang terjadi di Sumatera adalah hasil kejahatan agraria-SDA, pengkhianatan terhadap konstitusi, cerminan tata kuasa dan tata kelola agraria dan kehutanan yang buruk dan koruptif,” tutur Dewi.
Parahnya, lanjut Dewi, dalam satu tahun terakhir ini belum ada perbaikan fundamental bagaimana cara negara mengurus tanah dan hutan, sekaligus memenuhi konstitusionalitas rakyat. Selain secara serius dan cepat menangani bencana dan dampak sosial yang diderita masyarakat Sumatera, pasca-bencana, perubahan pradigmatik dan struktural tidak bisa lagi ditawar, maka pemerintah dan DPR harus berbenah diri.
Selain itu, berkaca pula pada aksi-aksi kemarahan rakyat dari Agustus hingga September, sudah seharusnya Anggota DPR semakin ketat dalam menjaga lisan, tindakan dan kepercayaan rakyat. Sebaiknya tidak mempolitisasi bencana di tengah derita rakyat Sumatera, serta segera mengasah literasi dan pengetahuan agar tidak kerap mengeluarkan statement yang mengundang kontroversi, kekecewaan dan kemarahan rakyat.
“Kami juga mengingatkan dan mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk menjalankan komitmennya dengan menempatkan reforma agraria sebagai arah transformasi tata kuasa dan tata kelola agraria dan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ucap Dewi.
Dewi menegaskan, tragedi ekologis di Sumatera justru terjadi karena reforma agraria yang sejati dan sesuai mandat konstitusi tidak kunjung dijalankan. Penyelenggara negara justru kalap memberikan tanah dan hutan kepada korporasi, termasuk korporasi yang terafiliasi pada perusahaan asing. Membiarkan monopoli tanah dan hutan oleh swasta yang sebenarnya dilarang oleh UUPA.
Menurut Dewi, pernyataan ngawur anggota DPR tentang reforma agraria menunjukkan bahwa masih banyak anggota dewan dan partai politik tidak memahami mandat konstitusi, reforma agraria dan akar masalah struktural agraria di negara kita. Pernyataan sesat itu, seolah-olah sudah ada tanah dan hutan yang dibagi-bagikan kepada rakyat marjinal sehingga bencana terjadi, dan anggota dewan tersebut memaknai reforma agraria sekedar sebagai bagi-bagi tanah hutan.
Dewi bilang cara pandang tersebut merupakan sesat-pikir, pertama, reforma agraria belum dijalankan sesuai mandatnya, kedua, reforma agraria bukan membagikan tanah hutan, ketiga, ada problem struktural agraria-kehutanan yang akut dan tidak dipahami, dimana banyak tanah rakyat, puluhan ribu desa, pemukiman, lumbung pertanian rakyat, wilayah adat dan hutan adat yang diklaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan berpuluh-puluh tahun lamanya—inilah praktik domein verklaring jaman kolonial yang masih dijalankan hingga saat ini.
“Termasuk rusaknya budaya agraris dan kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Itulah mengapa reforma agraria harus dilakukan bagi pemulihan hak rakyat sesuai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945,” ujar Dewi.
Bagi yang tidak kunjung paham, sambung Dewi, reforma agraria adalah usaha sistematis sebuah negara untuk melakukan perlindungan, pemulihan dan pengakuan hak atas tanah serta wilayah hidup masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan keberlanjutan alam dan memperbaiki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan hutan (adat).
Selain itu, reforma agraria juga adalah upaya menyelesaikan konflik agraria melalui mekanisme pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan wilayah adat, serta memulihkan tempat hidup, lahan kritis dan fungsi ekologis oleh rakyat secara mandiri berdasarkan kearifan lokal di lokasi-lokasi dimana reforma agraria dijalankan.
Sebelumnya, Firman Subagyo dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung DPR RI, Kamis, 4 November 2025, menyebut setelah reformasi hutan di Indonesia hancur, dan meminta agar reforma agraria dihentikan. Ia menganggap reforma agraria juga salah satu penyebab kerusakan hutan. Sayangnya, anggota DPR tersebut tidak menjelaskan secara substansial dasar dari tuduhan tersebut.
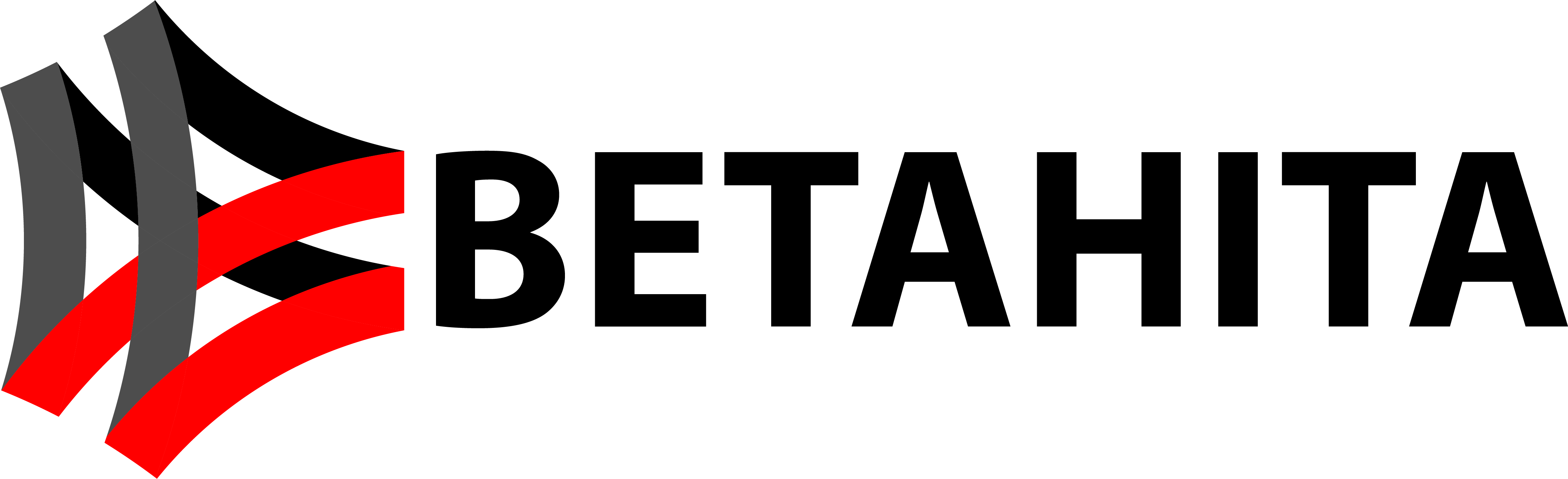


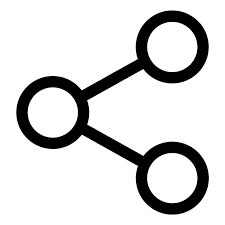 Share
Share

