Keselamatan Kerja Ditinggal Hilirisasi Nikel
Penulis : aryo bhawono
HAM
Kamis, 06 November 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Angka kecelakaan kerja di industri pengolahan nikel terus meningkat saban tahun. Penyakit akibat pencemaran dan kondisi lingkungan buruk pun turut mengancam keselamatan pekerja.
Keselamatan kerja para buruh komplek kawasan industri smelter seolah berbanding terbalik dengan klaim nilai ekspor nikel. Industri itu tercatat memberikan kontribusi ekonomi signifikan, dengan nilai ekspor produk hasil hilirisasi mencapai Rp 127 triliun (3 persen dari total nilai ekspor Indonesia pada akhir tahun 2024).
Namun kabar miris kecelakaan kerja sektor ini masih terus meningkat. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Kementerian Ketenagakerjaan, Hugo Nainggolan, menyebutkan pengawasan lembaganya mencatat setidaknya 104 kejadian kecelakaan kerja pada tahun 2019 hingga 2025, yang menyebabkan kematian 107 jiwa dan 105 orang luka-luka.
“Tingginya tingkat kecelakaan kerja di industri nikel disebabkan oleh lemahnya pengawasan, peralatan tidak layak, dan SOP keamanan yang tidak diterapkan,” ujarnya dalam diskusi “Menjamin Perlindungan Pekerja dan Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Nikel” yang diselenggarakan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) pada Senin lalu ((3/11/2025).

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaganya masih memiliki keterbatasan. Setidaknya Kemnaker menugaskan sekitar 1.400 orang yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Meski demikian, Hugo belum menyebutkan secara spesifik jumlah pengawas yang menangani aspek K3 di industri smelter nikel.
Ia berharap masyarakat dan pekerja dapat ikut turut serta untuk mengawasi implementasi K3 di lapangan. Kemnaker sendiri memiliki platform digital berupa Lapor Menaker yang bertujuan sebagai sarana pengaduan masyarakat dengan jaminan kerahasiaan data pelapor untuk dapat mempercepat penanganan pelanggaran oleh perusahaan.
Hendra, perwakilan pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) menyebutkan keselamatan pekerja masih sangat minim di daerah industri nikel. Bahkan para pekerja sering mendapatkan sanksi ketika berserikat dan menolak kerja yang berbahaya.
“Beban kerja tinggi, jam kerja panjang, dan minimnya pengawasan perusahaan membuat pekerja terus berada dalam kondisi bahaya. Banyak kecelakaan disalahkan pada pekerja, padahal fasilitas dan SOP tidak memadai,” ujar buruh di salah satu tenant di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ini.
Hendra menyoroti kondisi buruh perempuan yang menghadapi risiko K3 yang berbeda. Fasilitas dasar seperti toilet sering kali tidak tersedia di area kerja atau berjarak terlalu jauh, sehingga memaksa pekerja menahan buang air kecil dan memicu infeksi saluran kemih (ISK), yang banyak dialami oleh buruh perempuan. Ia juga menegaskan bahwa ancaman pelecehan di tempat kerja masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian dan perlindungan memadai.
Peneliti AEER Riski Saputra, periset lingkungan AEER, menyebutkan keterkaitan perlindungan lingkungan dan keselamatan pekerja. Ancaman baru terhadap pekerja dan lingkungan datang dari pengelolaan limbah tailing B3 hasil proses High Pressure Acid Leaching (HPAL).
Menurut Riski, sistem dry stack tailing memiliki risiko tinggi terhadap longsor karena umumnya dibangun di wilayah dengan curah hujan tinggi dan aktivitas seismik aktif. Volume limbah yang diproyeksikan mencapai 78 juta ton/tahun seiring peningkatan produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).
“Pemerintah perlu segera menyusun dan menerapkan standar nasional K3L untuk pengelolaan tailing HPAL dan membentuk lembaga pengawas tailing lintas sektor untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar,” ucapnya.
Selain itu ia juga menyoroti persoalan lama yang belum terselesaikan, yakni polusi udara dari PLTU batubara captive yang digunakan untuk menyuplai energi ke industri smelter nikel.
Beban polusi ini turut ditanggung oleh masyarakat di sekitar kawasan industri. Sebagai contoh, di Morowali, jumlah kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meningkat tajam dari 20.508 kasus pada tahun 2021 menjadi 80.713 kasus pada tahun 2024.
Selain ISPA, masyarakat juga melaporkan peningkatan penyakit kulit yang diduga disebabkan oleh debu batubara serta penurunan hasil tangkapan ikan yang berimbas pada pendapatan nelayan.Dari sisi regulasi, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menilai bahwa regulasi yang berlaku, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sudah tidak lagi relevan dengan kondisi industri saat ini dan perlu segera diperbarui.
Sementara itu, menjawab isu polusi, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, RR Sri Gadis Pari Bekti, menekankan urgensi penerapan industri hijau. Industri hijau sendiri tidak hanya dalam bentuk dekarbonisasi, tetapi juga mencakupi CSR berkelanjutan dan manajemen K3 yang memenuhi syarat.
“Sertifikasi industri hijau, perusahaan perlu memenuhi standar industri hijau dimana dalam standar ini, aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja juga harus memenuhi syarat,” kata dia.
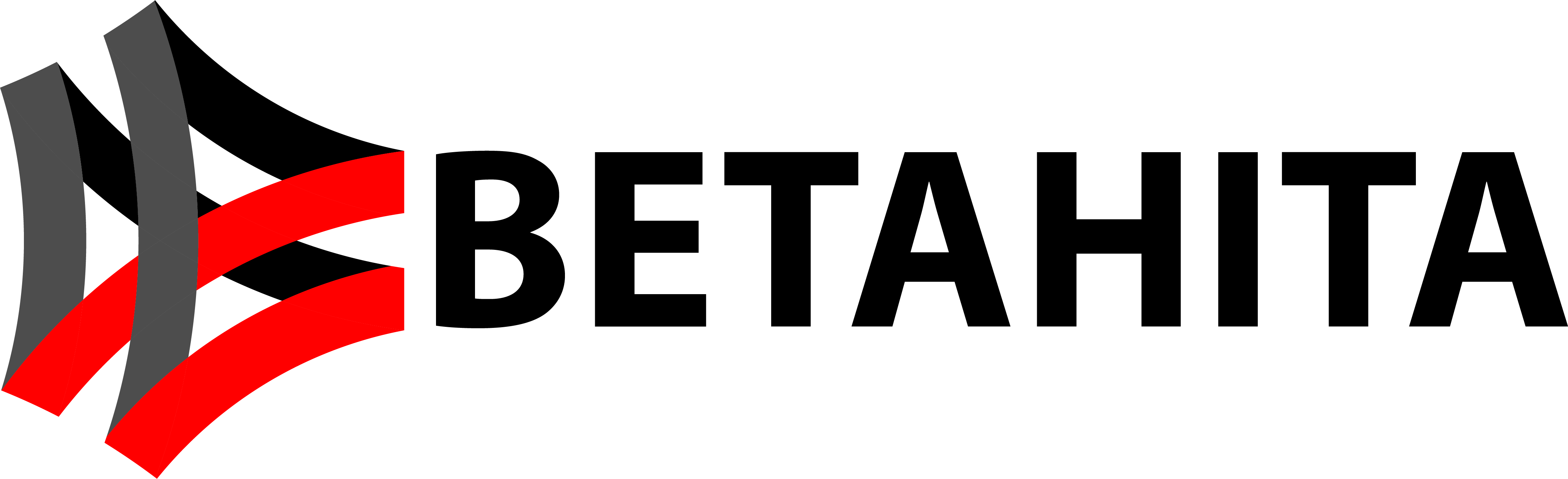


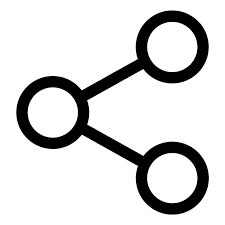 Share
Share

