Pelanggaran Lingkungan dan HAM Meluas dalam Industri Nikel - CRI
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Tambang
Jumat, 17 Oktober 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Pemerintah Indonesia dan sejumlah perusahaan yang mengoperasikan penambangan dan pengolahan nikel, semestinya segera mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran terhadap masyarakat setempat, mencegah serta membersihkan pencemaran udara dan air beracun, serta menghentikan penggunaan batu bara milik perusahaan untuk mendukung industri tersebut. Demikian disampaikan Climate Rights International (CRI) dalam laporan terbaru yang diterbitkan Kamis (16/10/2025).
Untuk menghasilkan laporan setebal 129 halaman berjudul Apakah Ada yang Peduli?” Dampak Industri Nikel di Indonesia terhadap Manusia, Lingkungan dan Iklim, itu CRI mewawancarai 93 orang yang tinggal di sekitar atau bekerja di lokasi penambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara—tiga lokasi utama industri nikel Indonesia.
Masyarakat melaporkan parahnya pencemaran udara dan air, sejumlah masalah kesehatan yang terkait dengan pertambangan, hancurnya mata pencarian nelayan dan petani, minimnya akses terhadap informasi kesehatan publik, perampasan tanah, kompensasi yang tidak adil untuk tanah mereka, kondisi kerja yang berbahaya, ancaman terhadap cara hidup masyarakat adat, intimidasi oleh aparat keamanan, dan ketakutan akan pembalasan jika nekat mengungkapkan kebenaran.
Peneliti di Climate Rights International, Krista Shennum, mengatakan menjelang Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Brasil, Pemerintah Indonesia semestinya menunjukkan kepemimpinan yang berarti dengan mengumumkan rencana ambisius dan terikat waktu untuk mendekarbonisasi berbagai proyek batu bara dan menghentikan penggundulan hutan sebagai akibat dari penambangan nikel.

“Transisi energi global tidak sepatutnya ditopang oleh praktik-praktik merusak lingkungan yang telah dilakukan selama puluhan tahun oleh industri ekstraktif. Hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain yang berada di garis depan penambangan mineral harus sepenuhnya dihormati,” katanya dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (16/10/2025).
Pada Januari 2024, CRI sebelumnya menerbitkan laporan berjudul Nikel Dikeduk, yang mengulas dampak lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan keberadaan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) senilai miliaran dolar dan tambang nikel di sekitarnya di Halmahera, Maluku Utara, serta pada Juni 2025 dalam laporan berjudul Perusakan Berlanjut dan Rendahnya Akuntabilitas.
Shennum menuturkan, industri nikel di Indonesia sangatlah besar. Sejak 2016, jumlah pabrik peleburan nikel di negara ini telah meningkat dari dua menjadi lebih dari 60, meninggalkan jejak kerusakan di sepanjang perjalanannya. Indonesia memasok lebih dari setengah produksi nikel dunia; ekspor produk turunan nikel dilaporkan mencapai USD38-40 miliar pada 2024.
Sebagian besar nikel diekspor untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan baterai yang digunakan dalam energi terbarukan, termasuk untuk kendaraan listrik. Namun, sejumlah perusahaan multinasional yang mendapat manfaat dari rantai pasokan ini tidak berbuat banyak untuk mengatasi berbagai praktik eksploitatif tersebut.
Penggunaan batu bara secara berlebihan dan pelanggaran HAM
Dalam laporan itu, CRI beranggapan, peralihan ke energi terbarukan merupakan kunci untuk mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil. Namun, industri nikel Indonesia berkontribusi pada emisi dalam jumlah besar yang memperparah krisis iklim. Hal ini disebabkan oleh pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru yang mendukung kegiatan industri nikel, tapi tidak menyediakan listrik untuk masyarakat setempat.
Shennum mengatakan, di seluruh Indonesia, pembangkit listrik tenaga batu bara yang terkait dengan proyek nikel memiliki kapasitas pembangkit sebesar 11,6 GW, dengan tambahan 5,5 GW sedang dalam proses pembangunan dan 1,5 GW dalam tahap pra-izin. Jika sepenuhnya dikembangkan, kapasitas seluruh pembangkit ini akan setara dengan kapasitas semua pembangkit batu bara di Thailand dan Filipina yang digabungkan.
Meski demikian, pembangkit batu bara yang dimiliki sendiri (captive) tidak diwajibkan menjalani penilaian dampak lingkungan secara individual, tidak dikenakan kewajiban pelaporan emisi gas rumah kaca, dan tidak termasuk dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Indonesia dalam Perjanjian Paris.
Di kawasan-kawasan utama tambang nikel di Indonesia, proses pembebasan lahan ditandai dengan praktik perampasan lahan, kompensasi yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, serta penjualan lahan yang tidak adil. Orang-orang yang bersuara atau memprotes biasanya menghadapi intimidasi, pelecehan, atau balas dendam.
“Dalam beberapa kasus, warga masyarakat menyatakan bahwa penggunaan aparat kepolisian atau militer oleh perusahaan nikel telah menghalangi mereka untuk bersuara menentang perampasan lahan maupun pencemaran lingkungan yang serius,” kata Shennum.
Menurut Shennum, operasi penambangan dan pengolahan nikel tengah mengancam hak warga lokal atas air minum yang aman dan bersih, karena aktivitas industri dan penggundulan hutan mencemari saluran air yang menjadi sumber kebutuhan dasar warga setempat. Masyarakat adat dari komunitas Bajau, Kaliki, dan Mori serta penduduk pedesaan lainnya tengah menghadapi ancaman eksistensial terhadap mata pencarian dan budayanya.
Perusakan hutan, perampasan lahan pertanian, menurunnya kualitas sumber daya air, dan kerusakan habitat perikanan akibat industri nikel telah mempersulit, jika tidak mustahil, untuk melanjutkan cara hidup tradisional. Di beberapa desa di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, perusakan ekosistem telah memicu meningkatnya konflik antara manusia dan buaya.
Shennum menyampaikan, di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, masyarakat yang tinggal di dekat proyek nikel juga khawatir bahwa masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan, tengkes alias stunting pada anak-anak, serta gangguan kesehatan lainnya, terkait dengan polusi debu dari tambang nikel dan operasional pabrik peleburan, fasilitas pengolahan, serta pembangkit listrik tenaga batu bara yang dimiliki sendiri.
Para pekerja di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) seluas 5.500 hektare di Sulawesi Tengah menggambarkan sejumlah pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang sistematis, termasuk risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Kalangan pekerja perempuan menghadapi risiko tambahan, termasuk diskriminasi berbasis gender, pelecehan seksual, risiko kesehatan reproduksi akibat paparan bahan beracun, dan fasilitas yang tak memadai.
“Pada proyek-proyek industri bernilai miliaran dolar di seluruh Indonesia, secara de facto masyarakat lokal kini berada di ‘zona pengorbanan’, di mana ekstraksi nikel mengorbankan kesehatan, mata pencarian, dan hak-hak mereka,” kata Krista Shennum.
Shennum menambahkan, perusahaan-perusahaan Indonesia, Tiongkok, dan asing lainnya memanfaatkan krisis iklim untuk mengekstraksi nikel dengan cara tidak adil, merugikan, sekaligus menghasilkan karbon yang tinggi. Bukannya melindungi masyarakat dan lingkungan, pemerintah justru secara aktif mendukung industri ini yang menginjak-injak masyarakat adat dan komunitas lain.
Tanggung jawab pemerintah dan korporasi
CRI mencatat, setahun setelah Prabowo Subianto menduduki kursi kepresidenan, pemerintahannya terus secara aktif memprioritaskan industri nikel di atas kesejahteraan warganya. Pemerintah Indonesia seharusnya segera memperkuat undang-undang dan peraturan untuk meminimalkan dampak penambangan dan pengolahan nikel terhadap masyarakat, termasuk komunitas adat.
Pemerintah juga semestinya segera menghentikan pemberian izin untuk semua pembangkit listrik batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang dimiliki sendiri (captive) yang digunakan untuk memasok energi ke kawasan industri nikel.
Shennum berpendapat, diperlukan regulasi dan pengawasan pemerintah yang tegas, serta uji kelayakan korporasi yang lebih ketat, guna memastikan bahwa industri mineral transisi yang sedang berkembang dan rantai pasokannya tidak meniru praktik perburuhan dan lingkungan yang buruk dan telah lama menjadi ciri industri ekstraktif di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Tapi selama satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia justru telah mengesahkan sejumlah kebijakan dan undang-undang yang memprioritaskan pertumbuhan industri nikel, melemahkan perlindungan lingkungan dan hak-hak komunitas adat, serta memperkuat peran militer.
Pada Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memungkinkan anggota militer aktif untuk menduduki jabatan sipil. Berbagai kelompok hak asasi manusia khawatir hal ini dapat memperluas penggunaan kekuatan militer serta mengurangi akuntabilitas di wilayah-wilayah yang terdampak industri ekstraktif.
Kerusakan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat disebabkan oleh aktivitas banyak perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel, termasuk di beberapa kawasan industri nikel terbesar di negara ini dan perusahaan-perusahaan seperti Indonesia Morowali Industrial Park, PT Gunbuster Nickel Industrial, Harita Nickel, Virtue Dragon Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel, dan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
“Perusahaan nikel seharusnya segera mengambil berbagai langkah guna mengatasi pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh operasinya, serta membuang limbah tambang dengan benar untuk meminimalkan pencemaran lingkungan,” kata Shennum.
Shennum berpendapat, perusahaan-perusahaan itu seyogianya memberikan kompensasi yang penuh dan adil kepada semua anggota masyarakat, termasuk masyarakat adat, atas tanah mereka, dan memastikan mereka memperoleh Persetujuan Atas Dasar Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC), sebagaimana ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional.
Menurut CRI, lanjut Shennum, sejumlah perusahaan kendaraan listrik dan baterai yang menggunakan nikel dari Indonesia semestinya segera memanfaatkan pengaruh mereka untuk memastikan bahwa para pemasok menghentikan dan memberikan ganti rugi atas terjadi pelanggaran hak asasi manusia, membersihkan air dan udara yang tercemar, serta beralih dari batu bara ke sumber energi terbarukan sesegera mungkin. Perusahaan-perusahaan tersebut juga semestinya meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi publik tentang semua perusahaan dalam rantai pasokan mineral transisi mereka.
“Karena lebih dari separuh pasokan nikel dunia berasal dari Indonesia, sebagian besar perusahaan kendaraan listrik dan produsen baterai menggunakan nikel Indonesia dalam baterai mereka,” kata Shennum.
“Untuk mempertahankan kredibilitas mereka sebagai bagian dari solusi krisis iklim, industri kendaraan listrik harus mendesak perusahaan nikel agar menghormati hak-hak masyarakat, menghentikan berbagai praktik yang merusak lingkungan, dan tak lagi menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk pengolahan nikel,” imbuhnya.
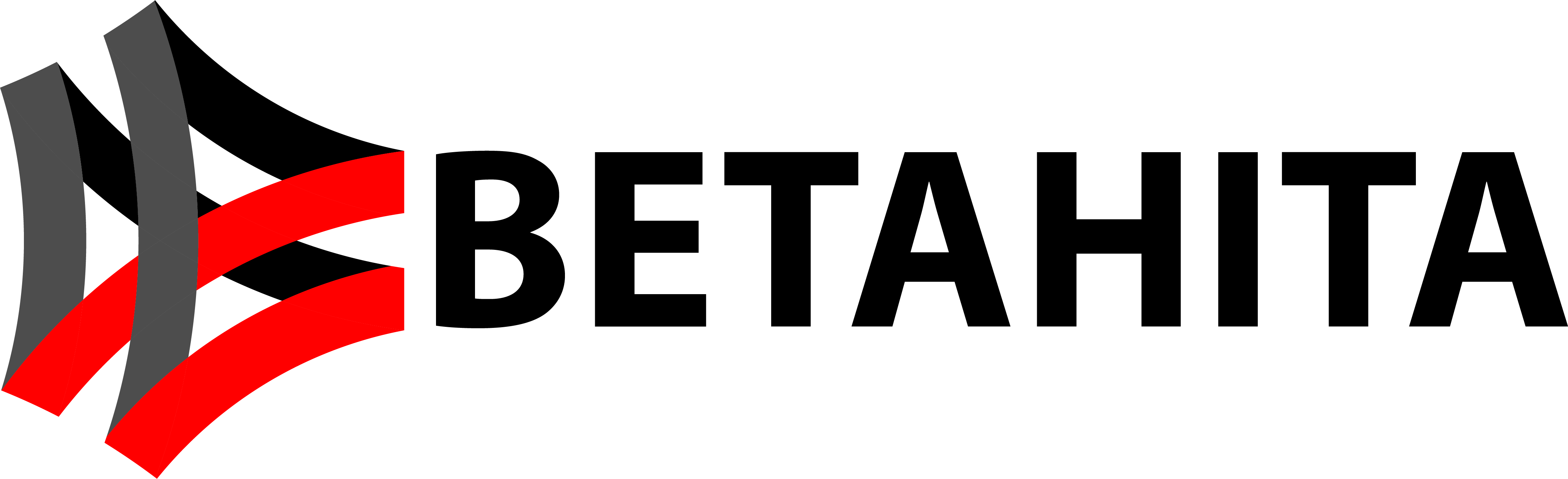


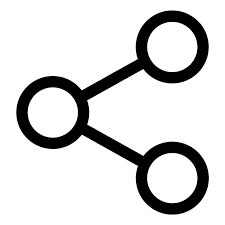 Share
Share

