Kontrol Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial di Papua
Penulis : MA. Mahruz, YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT
OPINI
Senin, 07 Juli 2025
Editor : Yosep Suprayogi
MEMAHAMI permasalahan di Papua, terutama bagaimana hutan dikelola dan dieksploitasi bisa dimulai dari melacak akar “hutan politik” yang dipraktikkan sejak masa kolonial Belanda hingga pengelolaan hutan di Jawa pasca Indonesia merdeka (Nancy lee Peluso, 1994). Hutan politik bekerja melalui logika teritorialisasi atau negaraisasi hutan dengan cara mengontrol orang dan aktivitasnya. Dalam hal ini melalui penciptaan garis batas di sekeliling ruang geografis, dan menghalangi orang-orang tertentu masuk ke suatu wilayah, menerapkan aturan pengecualian melalui (dengan) mengizinkan atau melarang aktivitas di dalam batas-batas ruang tersebut (Vandergeest P, 1996). Berpijak dari definisi ini teritorialisasi wilayah menjadi kawasan hutan negara, didasari oleh klaim monopoli kepemilikan atau penguasaan negara secara sepihak bahwa semua wilayah hutan yang tidak dimiliki dinyatakan sebagai hutan negara. Hutan politik dengan begitu juga berarti upaya mendenaturalisasi hutan, melalui pendefinisian ulang makna hutan menjadi entitas politik-ekologi yang terbentuk melalui suatu kombinasi wacana kolonial, strategi tata kelola wilayah, dan munculnya kehutanan ilmiah (Peluso, Vandergeest, 2001, J. A. Devine, 2020).
Secara empiris hutan politik (political forest) dengan definisi di atas telah memproduksi perampasan tanah rakyat yang menyejarah. Bahkan residunya yang tak lekang waktu itu turut serta memproduksi kesinambungan konflik agraria struktural. Dalam konteks Indonesia, perubahan politik dan hukum karena badai kemerdekaan 1945 tidak banyak mengubah keadaan pada tingkat akar rumput (masyarakat). Meskipun asas domein verklaring (pernyataan kepemilikan) oleh negara kolonial Belanda dihapuskan melalui Pasal 33 UUD 1945 dan UU No.5/1960 tentang Pokok Agraria, perubahan konfigurasi politik pasca 1965 membentuk politik hukum kehutanan yang beroperasi dengan mengabaikan ketentuan itu salah satunya melalui UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. UU Kehutanan ini dibentuk tidak dimaksudkan untuk menghapus domein verklaring dalam UU Kehutanan Kolonial Belanda, melainkan tetap mempertahankannya melalui pengelolaan Jawatan Kehutanan (menjadi Perhutani) (Noer Fauzi Rachman, kawasan hutan sebagai masalah agraria yang menyejarah, 2020). Suatu perubahan yang secara politik hukum dapat dibaca sebagai kebangkitan rezim hukum dan pembangunan atau secara ekonomi-politik dapat dibaca – meminjam istilahnya Richard Robinson – sebagai “kebangkitan kapitalisme Indonesia” (Richard Robison, 2012).
Tulisan ini berperan menjelaskan regulasi perhutanan sosial dan penerapannya di Papua, terutama Papua Barat Daya yang berkorelasi dengan cara negara mempertahankan kawasan hutan negara. Argumen ini akan dibangun berdasarkan temuan lapang dan landasan kebijakan dan teori yang terkait.
Ekstraksi Hutan Papua
Sejarah hutan politik yang beroperasi di Papua tidak lepas dari pengaruh UU No.5/1967 yang mempertahankan asas domein verklaring bahwa semua hutan yang berada di wilayah Indonesia adalah hutan negara. Klaim monopoli ini diterapkan di hutan Papua tahun 1982 melalui surat keputusan Menteri Pertanian No. 820 Tahun 1982 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Irian Jaya hampir seluas 41 juta ha sebagai Kawasan Hutan Negara. Sebagai bentuk kontrol hutan politik, pada 1989-1997 Departemen Kehutanan mengeluarkan izin operasi 40 perusahaan HPH di Papua (Jurnal Wacana, Insist Press, 2005). Catatan Forest Watch Indonesia (2021) menyebut pengusahaan hutan Papua dikuasai oleh 46 perusahaan melalui konsesi HPH dan HTI. Proses penciptaan kontrol atas wilayah hutan tersebut tentu saja tidak melibatkan orang asli Papua dan dalam konsesi itu menyimpan sejarah perampasan tanah adat orang-orang asli Papua seperti terjadi pada Gelek Malak Kalawilis Pasa, sub suku Moi di Sorong yang hutan adatnya masuk dalam HPH PT Intimpura Timber, Grup KLI seluas 333.000 ha (Pusaka, 2024). Dalam banyak situs industri ekstratif di Papua, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ini menjadi induk semang dari bisnis lanjutan seperti HTI, hingga perkebunan sawit.

Mempertahankan hutan negara berarti menciptakan alat kontrol berupa regulasi untuk mengatur fungsi kawasan hutan negara (HPK, HL, HK) dan pengelolaan bisnis kehutanannya. Regulasi juga diperankan untuk mengalokasikan sumberdaya publik (hutan) melalui macam-macam skema konsesi seperti HPH, - kini perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan Perhutanan Sosial. Dua kategori terakhir merupakan kepengaturan paling baru yang diproduksi rezim Pembangunan Joko Widodo.
Situasi kini tak berubah. Sejarah nampak berulang. Laporan majalah Tempo (Juni, 2025) menunjukkan, ibarat memanen hutan politik, pemerintah melayani banyak perusahaan yang mengusulkan PBPH di hutan Papua sejumlah 15 PBPH atau seluas 1.37 juta ha kawasan hutan. Walaupun di lapangan jumlah ini tentu saja tak menggambarkan bagaimana prosesnya yang mengabaikan partisipasi masyarakat, memicu konflik terencana, tertutup dan sentralisasi perizinan terpusat karena sejak semula desain regulasinya menghendaki demikian (Konflik Terencana Pemanfaatan Hutan pasca UU Cipta Kerja, Tempo, 2025).
Mempertahankan Hutan Politik di Papua
Apa yang disebut mempertahankan hutan politik di sini adalah mempertahankan hutan negara, guna dikontrol dan dialokasikan pemanfaatannya. Beberapa contoh konsesi di atas merupakan konsekuensi dari kontrol atas kawasan hutan yang memudahkan alokasi untuk tujuan bisnis. Namun hutan politik juga berhubungan dengan pendefinisian kontrol hutan negara yang membentuk hubungan masyarakat, wilayah dan sumberdaya melalui perubahan hukum/kebijakan yang didesain mengakomodasi berbagai macam kepentingan dalam aturan yang saling berkontestasi. Dalam format ini berbagai kelompok disediakan pilihan-pilihan dalam regulasi untuk mendapatkan kepentingannya yang mana sangat bergantung pada kuasa yang dimiliki. Perubahan ini juga respon dari perubahan kebijakan yang didorong dari luar, misal pengaruh Putusan MK 35 dan tuntutan paradigma pengelolaan SDA secara global.
Berangkat dari adanya perubahan pola kontrol hutan negara, yang berimplikasi pada hutan di Papua, negara sejatinya masih sangat berkuasa atas sumberdaya hutan di Papua. Bagaimana cara mempertahankannya, secara spesifik di sini memerankan perhutanan sosial dengan skema hutan desa/kampung yang semakin dipaksakan penerapannya di tingkat tapak sebagai bagian dari agenda teritorialisasi atas hutan Papua. Berpijak pada desain regulasinya Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial mempunyai lima skema; hutan desa/kampung, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, terakhir hutan adat. Kecuali hutan adat, empat skema lainnya dapat menjadi senjata hukum (weaponizing of the law) untuk mempertahankan kawasan hutan negara karena tidak mengubah kontrol hutan negara. Sebaliknya hutan adat – merupakan kategori hukum berbeda setelah Putusan MK 35 yang secara fundamental mengoreksi kesalahan hutan negara dengan konsekuensi hukum lepas dari kontrol hutan negara. Dengan desain aturan itu, pemerintah mempunyai kemampuan untuk memanipulasinya sebagai alat untuk mempertahankan hutan negara dan elit politik-ekonomi untuk mengambil keuntungan darinya. Kemampuan manipulatif ini dimungkinkan karena karakter institusi politik Indonesia dibangun berdasarkan hubungan klientelistik yang beroperasi melemahkan kelembagaan dan hukum negara yang disebut Berenschot sebagai praktik backdooring of the law (Politik Kehutanan, Ward Berenschot, et.at, tanpa tahun). Ward mencontohkan banyaknya kasus di sektor kehutanan di Indonesia misalnya selalu diupayakan secara institusional untuk memperbaiki masalah di sektor kehutanan yang melanggar aturan di mana selalu dapat dihindari oleh aktor kuasa. Poin pentingnya adalah solusi institusional selalu dapat “diakali” karena akar masalahnya tak pernah “dibidik”.
Berdasarkan pijakan demikian, kemudian merujuk pada data resmi yang diumumkan oleh KLHK, menunjukkan banyaknya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan skema hutan desa/kampung, HKM atau lainya yang diberikan oleh negara di wilayah adat di Papua. Sementara sedikitnya hutan adat yang ditetapkan pemerintah (KLHK) dan tiadanya rekonfigurasi reguasi percepatan pengakuan menunjukkan ada fenomena politik pengelolaan hutan di Papua yang tak biasa.
Sebagai contoh, data KLHK hingga 2024 capaian perhutanan sosial di tanah Papua misalnya Prov. Papua hanya satu penetapan hutan adat, dan 63 SK Hutan kampung. Prov. Papua Barat satu penetapan hutan adat, dan 99 SK hutan kampung. Prov. Papua Barat Daya belum ada penetapan hutan adat, dan 70 SK hutan kampung. Terakhir Prov. Papua Selatan belum ada penetapan hutan adat, dan terdapat 76 SK hutan kampung.

Hutan Kampung (titik biru) pada Mei 2025. Sumber: KLHK, 2025
Data di atas menunjukkan fenomena hutan politik bekerja mengontrol hutan di Papua. Perlu ditekankan bahwa perwujudan dari kontrol sebagai watak dari hutan politik di Indonesia tidak hanya berupa pengelolaan hutan oleh negara melalui penerbitan konsesi kehutanan kepada korporasi misal melalui HPH/IUPHHK/PBPH, tetapi juga cara mempertahankan kontrol atas hutan negara. Yang dimaksud cara kontrol di sini adalah penciptaan pengaturan yang berguna untuk mempertahankan hutan negara, seperti perhutanan sosial skema hutan kampung. Cara mempertahankan hutan negara di Papua tidak hanya melalui regulasi, dalam praktiknya juga diikuti oleh aparat penegaknya dengan cara penuh akal muslihat yang legal mempromosikan hutan kampung.
Akal muslihat yang dimaksud adalah cara agen negara mempersuasi pemilik adat untuk menerima hutan kampung di dalam wilayah adat yang diklaim sebagai tawaran solusi untuk mempertahankan wilayah adat dari ancaman pendudukan perusahaan. Cerita masyarakat di Sorong Selatan menyatakan, “Dorang (orang pemerintah) datang ke kampung bilang hutan kampung bisa melindungi kami pu tanah adat dari perusahaan kelapa sawit.” Sebenarnya ini mengandung muslihat upaya mengakali hukum (walau tak melanggar hukum) seperti tidak memberikan informasi yang benar di awal ke orang adat bahwa memilih hutan kampung berarti menerima batasan waktu kelola (35 tahun) dan batasan luas kelola. Agen negara memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atas regulasi dan menunggangi rasa cemas sehari-hari mereka atas ancaman pendudukan raksasa perusahaan ekstraktif. Situasi ini kerap terjadi di Indonesia di mana pemerintah menawarkan program pembangunan kepada masyarakat yang dianggap tidak maju - hanya berbekal niat baik -, tanpa analisis memadai, akhirnya berujung pada permasalahan (Tania Li, The Will To Improve).
Agen negara juga mendapat tambahan kekuatan dari lembaga non-negara yang didorong oleh logika mempertahankan kelestarian hutan dengan cara menawarkan skema pengelolaan hutan yang mengandung kesamaan pandang yakni seolah meragukan kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan berdasar pengetahuan dan hukum lokalnya serta pula tidak memahami konteks sosio-antropologi masyarakat. Praktik ini merupakan konsekuensi dari perubahan hutan politik yang dibentuk oleh keterlibatan lembaga non-negara sebagai pengaruh paradigma pembangunan berkelanjutan, wacana konservasi dan perubahan iklim (J. A. Devine, 2020).
Namun pilihan sengaja yang barangkali didorong suatu paradigma tertentu ini dengan mudah memanipulasi keadaan dan kesadaran orang Kampung untuk bertindak seolah-olah sesuai kehendak (dan consent) mereka. Dalam jangka panjang maksud baik ini di baliknya menyimpan kelumpuhan sosial karena menyebabkan ketidakberdayaan hak (rightlessness) bagi masyarakat adat, -- merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok yang hidup serba kekurangan hak atau tak bisa menggunakan haknya secara penuh, meskipun secara legal formal hak-haknya diakui (Ward Berenschot & A. Dhiaulhaq, 2023). Alih-alih mendapatkan hutan adatnya, orang adat Papua justru tanpa sengaja – termanipulasi – turut serta mempertahankan hutan negara dengan memilih hutan kampung dan semakin menjauhkannya dari hak konstitusionalnya yakni hutan adat. Banyaknya pengusulan dan persetujuan hutan kampung menunjukkan fenomena ini.
Melihat fenomena ini, menyeret kita untuk curiga pada agenda hutan politik di Papua yang dominan bekerja sebagai landasan kebijakan negara untuk Papua, terutama sektor kehutanan untuk mempertahankan hutan negara. Konsekuensinya hutan Papua akan tetap menjadi objek penerapan dari kebijakan ekstraksi SDA – karena bertahannya kontrol hutan negara – sedangkan bagi masyarakat adat Papua, mereka mengalami kondisi semakin hampa hak atas adatnya, karena menghambat penegakan konstitusional atas hutan adat.
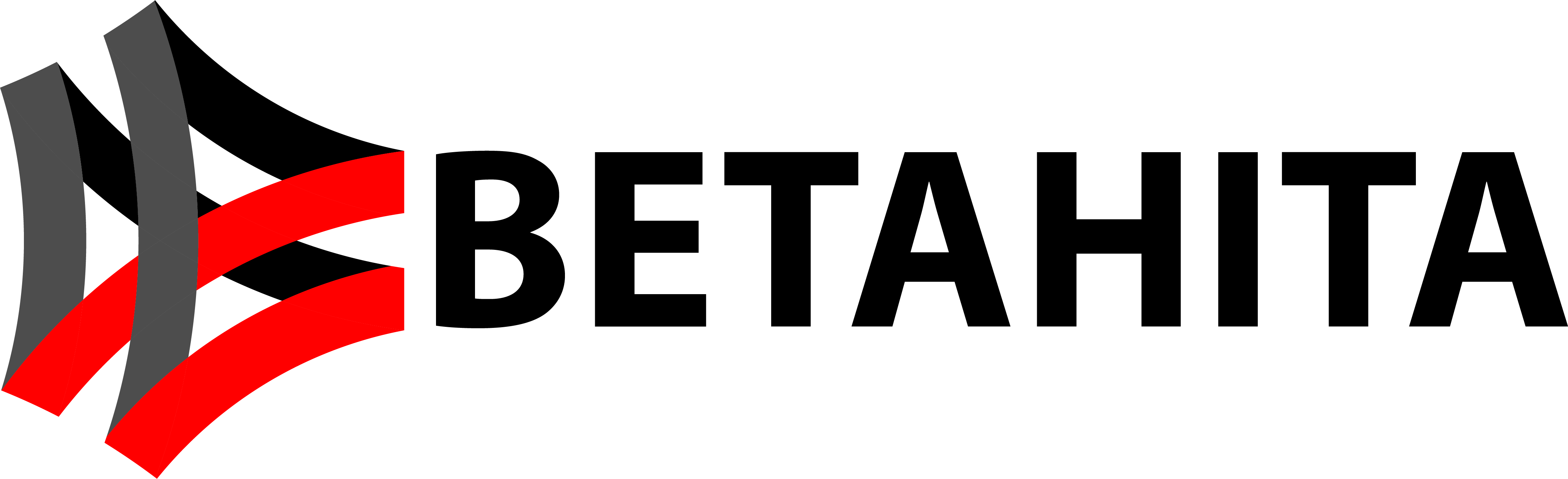


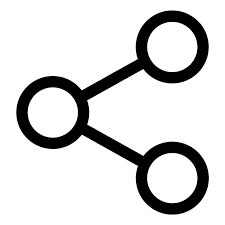 Share
Share

