Sulteng Bangkrut karena Nikel - Riset Jatam
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Tambang
Jumat, 23 Mei 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Sumber daya alam yang melimpah, terutama bahan mineral, tak membuat Sulawesi Tengah (Sulteng) jadi kaya. Yang terjadi justru bangkrut. Demikian menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, di momen peringatan Hari Anti Tambang (Hatam) 2025.
Jatam Sulteng menguraikan, menurut data Badan Geologi Kementerian ESDM (2020) cadangan biji nikel Indonesia adalah sebesar 4,5 miliar ton. Sulteng punya 1 miliar ton cadangan nikel. Dengan memiliki 22% dari cadangan nasional tersebut, Sulteng menjadi salah satu pusat ekstraksi (penambangan) yang diindikasikan dengan diterbitkannya 125 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) nikel.
Selain itu, Sulteng juga merupakan pemilik kawasan industri pengolahan nikel dengan pembangunan 3 kawasan industri pengolahan nikel yaitu kawasan industri Indonesia Morowali Industri Park (PT IMIP) di Kecamatan Bahodopi, PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP) di Bungku Barat dan PT Stardust Estate Investment (PT SEI) Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
“Dengan semangat pemerintah menghilirisasi nikel, maka penambangan akan masif dilakukan untuk menyuplai material bagi smelter nikel yang ada di kawasan tersebut,” kata Moh. Taufik, Dinamisator Jatam Sulteng, Rabu (21/52025).

Taufik melihat, dalam hal ini pemerintah berkepentingan untuk membuka lapangan kerja dan mendapatkan nilai ekonomi melalui ekstraksi nikel dan pengolahannya. Pemerintah memprioritaskan tambang sebagai tumpuan ekonomi dengan memberikan perlindungan/penjaminan terhadap aktivitas ekstraksi ini melalui status Proyek Strategis Nasional, bahkan dua di antaranya yaitu PT IMIP dan PT SEI, ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Maka tidak mengherankan kawasan industri tersebut disetarakan dengan kawasan vital lain untuk mendapatkan kemudahan pengurusan izin dan selalu dijaga ketat oleh aparat negara baik polisi maupun tentara.
“Dari analisis yang kami lakukan terhadap data Minerba One Map Indonesia (MOMI) Dirjen Minerba yang diakses Juni 2024, terdapat 682 izin tambang yaitu itu mineral logam (nikel, emas, besi) sejumlah 131 izin dan tambang batuan (pasir, batu, batu gamping, dan lain-lain) 527 izin,” katanya.
Taufik mengungkapkan, luas konsesi tambang berdasarkan jenis izinnya (IUP, KK, dan WIUP/pencadangan) adalah sebesar 500.000 hektare. Jika dibandingkan dengan luas daratan Sulawesi Tengah sebesar 4 juta hektare, izin tambang di Sulteng mencaplok 12,5% dari daratan.
Dari 682 konsesi yang diberikan pemerintah tersebut, 125 adalah IUP nikel yang kesemuanya berstatus IUP OP, dengan 2 Kontrak Karya nikel PT Vale yang sebagian masuk wilayah administratif Kab. Morowali dan sebagiannya masuk wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Peta Sebaran Konsesi Tambang di Sulteng. Sumber: Jatam Sulteng.
Menurut Taufik, dengan masifnya izin tambang yang diterbitkan pemerintah, dan juga pembangunan kawasan industri, seharusnya Sulteng dapat menjadi provinsi yang maju dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Faktanya, kemiskinan di Sulteng ada di angka 11,77 pada semester I 2024, pada September 2023, angka kemiskinan masih di 12,41%, masih di atas rata-rata nasional 9,03%.
“Itulah yang disebut dengan kutukan sumber daya alam, wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah cenderung masyarakatnya tetap miskin dan menderita,” kata Taufik.
Masalah-masalah yang timbul dalam pertambangan
Taufik berpendapat, pertambangan sudah bermasalah sejak awal. Masalah pertama adalah tidak adanya konsultasi yang memadai dan bermakna antara perusahaan dengan masyarakat yang tinggal dalam wilayah ekstraksi maupun warga terdampak di luar wilayah ekstraksi yang biasa disebut “warga lingkar tambang”.
Memadai merujuk pada keterwakilan semua unsur warga baik aparat desa, petani, nelayan, warga miskin, perempuan, dan lain-lain. Sedangkan bermakna merujuk bahwa warga tidak hanya datang untuk jadi pendengar, tetapi mereka diberikan kesempatan yang cukup untuk berpendapat.
Tetapi faktanya, imbuh Taufik, masyarakat tidak dianggap dalam rezim perizinan ekstraksi. Berdasarkan data Jatam melalui pendampingan terhadap warga dalam kurun 10 tahun terakhir, di seluruh wilayah pusat ekstraksi besar seperti Kabupaten Morowali, Kabupaten Morut, dan Kabupaten Banggai, perusahaan-perusahaan tambang itu tidak melakukan konsultasi dengan mengundang seluruh perwakilan warga sebelum beroperasi.
“Jika pun ada pertemuan, kesepakatan yang terjadi hanya melalui elit-elit desa. Pelibatan warga biasanya terjadi saat perusahaan melakukan pembebasan lahan jika WIUP-nya ada di lahan warga,” ujar Taufik.
Taufik melanjutkan, banyak informasi yang tidak dibuka secara terang benderang oleh perusahaan maupun pemerintah. Tidak ada pihak yang menjelaskan dampak pertambangan secara berimbang. Para pihak yang hadir hanya menjelaskan mengenai nilai-nilai positif seperti bahwa tambang membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan peningkatan ekonomi.
Dokumen perizinan seperti IUP dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak dibuka untuk didiskusikan bersama warga terdampak. Diskursus mengenai dampak negatif kerusakan lingkungan seperti risiko pencemaran sumber air dan pesisir tidak dibicarakan secara serius.
“Persetujuan warga tidak diinginkan secara sungguh-sungguh. Sosialisasi kepada warga hanya untuk menyelesaikan kewajiban perintah undang-undang. Ini bukan kesadaran perusahaan untuk benar-benar berkonsultasi,” ujar Taufik.
Pemerintah, sambung Taufik, juga hanya menjadi fasilitator, paling jauh hanya sebagai moderator. Selain itu, dalam beberapa kasus, warga yang menolak tidak dilibatkan karena dianggap akan mengganggu stabilitas rapat.
Seluruh warga yang berada lingkar tambang seharusnya dihadirkan, tanpa melihat apakah mereka menerima dan mendukung aktivitas perusahaan atau menolak. Apabila sungai atau mata air tercemar akibat tambang, maka seluruh warga akan mengalami krisis air.
Dirunut lebih ke atas lagi, dalam penerbitan WIUP—berdasarkan definisi adalah wilayah izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan penambangan, tidak ada partisipasi warga. WIUP diterbitkan berdasarkan keputusan pemerintah setelah pemohon WIUP memenuhi syarat administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, dan finansial.
“Proses ini tanpa sekalipun melibatkan warga untuk diminta pendapatnya mengenai rencana pertambangan,” ucap Taufik.
Taufik mengatakan, kebijakan pengelolaan pertambangan diputuskan dari atas ke bawah. Penerbitan izin ada di gubernur yang tinggal di Palu—rezim perizinan tambang batuan, dan lain-lain, maupun menteri, tapi warga yang menghadapi masalah-masalah ketika pertambangan beroperasi tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan-kebijakan tersebut.
Sumber air tercemar
Aktivitas tambang juga mengakibatkan pencemaran air. Seperti yang terjadi di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Pada Juni 2022, terjadi banjir bandang di Desa Pongian yang menyebabkan tercemarnya Sungai Pongian oleh lumpur dari tambang. Warga, terkhusus yang tinggal di bantaran sungai kehilangan akses terhadap air bersih.
 Sungai Pongian tampak keruh saat musim hujan, pada 2024. Foto: Jatam Sulteng.
Sungai Pongian tampak keruh saat musim hujan, pada 2024. Foto: Jatam Sulteng.
Walhasil warga sudah tidak bisa menggunakan Sungai Pongian untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan rumah tangga lain seperti mandi dan mencuci. Ternak seperti sapi juga enggan untuk minum di sungai. Kendala ini menyebabkan beban bagi warga karena harus mengusahakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih padahal sebelumnya aksesnya hanya di belakang rumah-rumah warga.
Aktivitas PT Koninis Fajar Mineral diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang tersebut. Perusahaan ini memegang konsesi seluas 2.738 hektare, dan mulai melakukan operasi produksi pada 2020.
“Musibah seperti ini mudah ditemui di wilayah-wilayah ekstraksi sumber daya alam,” ucap Taufik.
Menurut Taufik, permasalahan lingkungan seperti kerusakan hutan, banjir, tercemarnya sumber air warga, disebabkan oleh karakteristik pertambangan yang eksploitatif dan masif sehingga bagaimanapun mekanisme yang dilakukan, pasti akan berdampak terhadap lingkungan dan warga sekitar.
Perempuan dan pengelolaan SDA
Taufik melanjutkan, perempuan adalah korban yang paling menderita ketika tambang beroperasi. Itu adalah klaim yang sudah terbukti di wilayah-wilayah yang menjadi pusat ekstraksi. Perempuan adalah pihak yang paling terpukul ketika sumber air tercemar.
Perempuan lebih membutuhkan air untuk kebutuhan dirinya dibanding laki-laki karena perempuan menstruasi dan melahirkan keturunan. Dalam kebudayaan patriarki seperti di Sulawesi Tengah, perempuan mengurus kebutuhan makanan, mencuci pakaian, dan berbagai aktivitas domestik lainnya yang membutuhkan air.
“Oleh sebab itu, ketika sumber air terganggu, rusak atau tercemar, perempuan yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Dengan banyaknya ketergantungan perempuan terhadap air, sangat disayangkan partisipasi perempuan dalam menentukan rencana pengelolaan sumber daya alam sangat minim. Dalam setiap rapat sosialisasi ketika tambang masuk, laki-laki mayoritas menghadiri pertemuan tersebut, perempuan dibebani mengurus rumah dan menyiapkan makanan.
Jika pun ada perempuan yang dihadirkan, biasanya hanya untuk mencapai keterwakilan saja, tetapi untuk berdialog langsung dengan para stakeholder dalam suatu partisipasi bermakna, mereka tidak diberikan kesempatan.
Tambang dan kemiskinan
“Dalam 10 tahun terakhir, eksploitasi SDA di sektor pertambangan sangat masif. Hal ini disebabkan adanya pembangunan smelter,” kata Taufik.
Secara singkat, pembangunan smelter merupakan amanat UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyebutkan bahwa IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
Taufik menuturkan, sejak Januari 2014, atau 5 tahun setelah UU Minerba disahkan, pemerintah mewajibkan membangun smelter dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah yang sering disebut dengan istilah hilirisasi. PT IMIP, imbuh Taufik, merupakan salah satu perusahaan pertama yang berkomitmen membangun smelter nikel di Indonesia.
“Pada 2017 PT IMIP melakukan uji coba produksi smelter-nya dan sejak saat itu, eksploitasi tambang meningkat dan semakin masif untuk menyuplai bahan mentah/ore nikel ke smelter,” ujar Taufik.
Taufik menguraikan, apabila disederhanakan, penambangan nikel dibagi menjadi 2 fase yaitu pra-hilirisasi 2009-2014, dan pasca-hilirisasi 2014-2024. Berdasarkan data kemiskinan 20 tahun terakhir yang diterbitkan BPS, pada periode hilirisasi 2014-2024 penduduk miskin di Morowali dan Morut turun dari 14,97% pada 2014, menjadi 11,75% pada 2024, atau berkurang 3,22% dalam 10 tahun.
Angka ini tampak membahagiakan, setidaknya bagi pemerintah yang selalu bereuforia bahwa tambang menurunkan kemiskinan di Morowali dan Morat. Tetapi, sambung Taufik, jika mengulik sedikit saja data-data tersebut, maka akan kita dapati fakta selanjutnya bahwa kemiskinan dalam 10 tahun pra hilirisasi, yaitu 2004-2014 lebih berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.
“Pada 2004, kemiskinan di Morowali-Morut adalah sebesar 25,53%, dan turun menjadi 14,97% pada 2014. Dengan kata lain kemiskinan di Morowali-Morut turun 10,56% dalam waktu 10 tahun–jauh di atas periode hilirisasi yang hanya 3,22%,” ucap Taufik.
Berdasarkan data jumlah orang miskin, Taufik melanjutkan, sebelum periode pra hilirisasi (2004-2014), yakni periode saat pemerintah berfokus mengekspor biji kakao, biji kelapa dan biji-biji hasil pertanian lain, jumlah penduduk miskin turun sejumlah 8.560 jiwa. Sedangkan pada periode hilirisasi, periode masifnya ekspor biji nikel, (2014-2024) kemiskinan di Morowali dan Morut turun hanya sejumlah 2.310 jiwa.
Angka-angka itu, imbuh Taufik, seolah membantah argumentasi bahwa pengentasan kemiskinan lebih besar disumbang dari hasil ekploitasi tambang. Karena periode pra-hilirisasi lebih berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan daripada pasca-hilirisasi.
“Mengapa pembukaan lapangan pekerjaan puluhan ribu orang di pabrik smelter kalah dengan ekonomi warga dari sektor pertanian dan perikanan? Mengapa ini bisa terjadi?” kata Taufik.
Tambang dan lapangan pekerjaan
Taufik menuturkan, pembukaan tambang selalu diidentikkan dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Asumsi selanjutnya adalah, jika lapangan pekerjaan terbuka, maka kemiskinan menurun. Celakanya itu hanyalah asumsi.
Pertambangan memang membuka lapangan pekerjaan, itu bisa dilihat dari jumlah pekerja yang diserap dalam beberapa kawasan industri seperti yang dilaporkan yaitu PT IMIP 84.000 pekerja, PT SEI yang diproyeksikan akan menyerap 60.000 pekerja, dst. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa, dalam waktu yang sama, pertambangan juga menutup lapangan pekerjaan lain.
“Misalnya apa yang terjadi di Desa Fatufia, Kabupaten Morowali di mana limbah PLTU yang dibuang ke laut, menyebabkan air laut panas dan pesisir rusak yang berdampak terhadap pengurangan jumlah tangkapan nelayan,” kata Taufik.
Di wilayah lain seperti di Desa Ganda-Ganda Kabupaten Morowali Utara, lanjut Taufik, pesisir pantai dan ekosistem karang yang menjadi rumah ikan dan biota laut rusak oleh lumpur merah dari lubang tambang yang ada di gunung-gunung di atas kampung. Akibatnya, nelayan susah mendapatkan ikan dan wilayah tangkap semakin jauh, yang menimbulkan efek domino besarnya biaya untuk membeli bahan bakar.
Di bidang pertanian, pertambangan berdampak terhadap tercemarnya pertanian warga. Pada Februari 2024, Di Desa Onepute Jaya, sawah petani tercemar limbah tambang yang terbawa oleh hujan yang menyebabkan petani merugi. Pada 2023, sekitar 40 hektare sawah di Desa Solonsa, Kabupaten Morowali lumpur dari aktivitas tambang masuk di persawahan warga yang baru selesai ditanam.
Jika menggunakan hitungan kasar jumlah pekerja yang terlibat dalam pengelolaan sawah sebesar 10 orang per hektarnya, maka ada 400 orang yang kehilangan pekerjaan, atau minimal terganggu pekerjaannya, akibat aktivitas tambang.
“Inilah dilema tambang itu. Ia membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menutup pekerjaan lainnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tambang mempunyai kompleksitas masalah yang dalam,” ujar Taufik.
Taufik menegaskan, tambang tidaklah abadi. Menurut beberapa perhitungan baik dari kalangan pemerintah maupun akademisi, cadangan nikel kita akan habis dalam 15 tahun, yang lain berpendapat 25 tahun.
“Lalu, setelah SDA habis dan menyisakan lubang-lubang tambang menganga dan pencemaran sungai, laut, dan ruang hidup, apa lagi yang akan diwariskan untuk anak cucu kita?” katanya.
Taufik menyarankan pemerintah untuk melakukan beberapa hal, yakni mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan yang sudah eksis untuk melihat secara jernih kesesuaian strategi pengelolaan SDA dengan tujuan sesuai amanat konstitusi yaitu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tak kalah penting, menghormati hak veto dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pengelolaan wilayahnya yang berkeadilan.
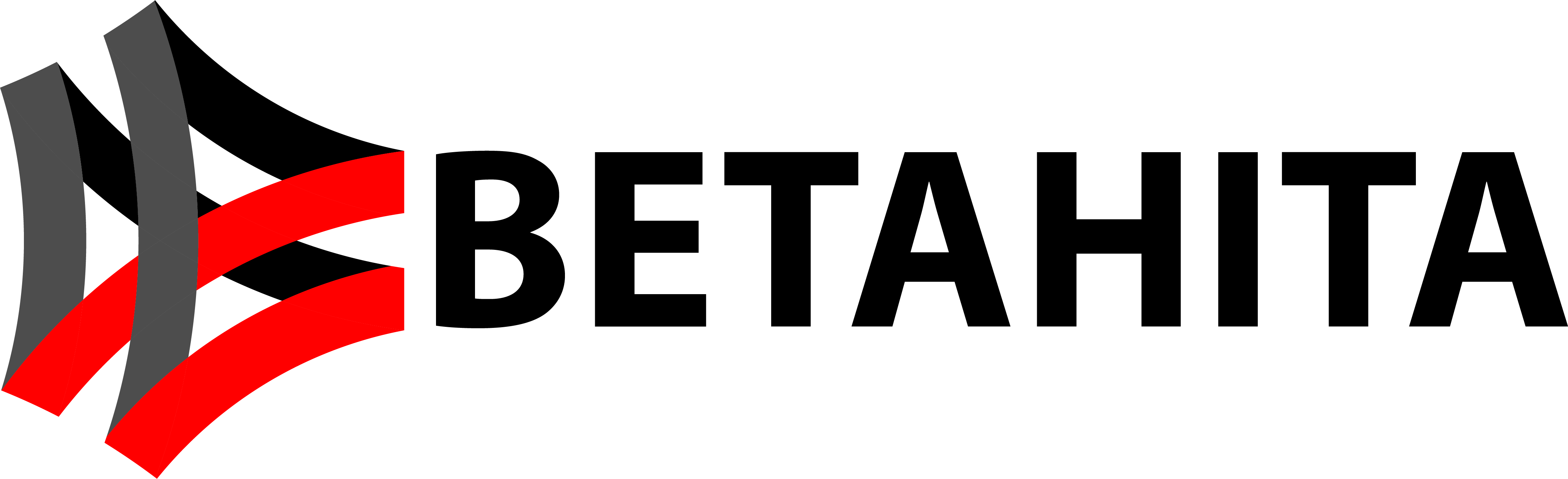


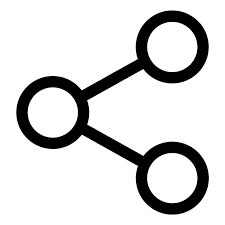 Share
Share

