
LIPUTAN KHUSUS:
Minta Tanam Sawit, Presiden Siapkan Bencana Ekologi di Papua
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Keinginan untuk membuka sawit dan kebun tebu skala besar di Papua hanya akan memperparah krisis ekologi.
Ekologi
Kamis, 18 Desember 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Permintaan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para kepala daerah se-Papua, agar Tanah Papua ditanami sawit dan tebu, menuai gelombang kritik dan kecaman dari kelompok masyarakat sipil. Dengan permintaan tersebut, Prabowo dianggap sedang menyiapkan bencana ekologis di Papua.
“Dan, juga nanti kita berharap, di daerah Papua pun, harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga, tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava, juga untuk menghasilkan etanol,” ujar Prabowo saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Papua, Selasa (16/12/2025).
Prabowo berharap, dalam lima tahun semua daerah di Papua bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, negara akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri.
“Tahun ini, tiap tahun, kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ujar Prabowo.

Kelompok masyarakat sipil menilai permintaan Presiden Prabowo itu menunjukkan tidak adanya kemauan politik untuk memperbaiki tata kelola hutan, lingkungan dan sumber daya alam, agar bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatera bagian utara, tidak lagi terulang atau bahkan meluas ke wilayah-wilayah lain.
Padahal besar harapan agar Prabowo memimpin proses evaluasi izin, penegakan hukum baik secara administratif (pencabutan izin) maupun pidana termasuk indikasi tindak pidana pencucian uang, menagih pertanggungjawaban korporasi untuk pemulihan lingkungan, serta koreksi kebijakan untuk melindungi ekosistem penting dan genting melalui moratorium permanen izin.
Uli Arta Siagian, Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, menganggap Presiden Prabowo seperti tak punya hati dan empati atas penderitaan rakyat di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, juga seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi korban pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Keinginan untuk membuka sawit dan kebun tebu skala besar di Papua hanya akan memperparah krisis ekologis,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).
Selama ini, lanjut Uli, rakyat Papua juga telah mengalami perampasan wilayah adat akibat izin-izin yang diterbitkan pengurus negara. Bahkan, pembukaan lahan 2 juta hektare untuk pangan dan energi yang sekarang berjalan dampaknya telah dirasakan oleh rakyat di Merauke, mulai dari perampasan wilayah adat, hilangnya sumber pangan lokal, banjir, kekerasan bahkan kriminalisasi.
Uli mengatakan, jika rencana ekspansi sawit, tebu dan lainnya atas nama swasembada pangan dan energi tetap dijalankan, sama artinya pengurus negara akan mengulang bencana ekologis Sumatera di Papua. Lebih jauh lagi, emisi yang akan dilepaskan dari perubahan hutan menjadi konsesi sawit, tebu dan aktivitas ekstraktif lainnya akan semakin memperparah krisis
“iklim. Anomali iklim, cuaca ekstrim adalah bahaya yang akan dihadapi oleh jutaan rakyat Indonesia,” ujar Uli.
Uli menganggap rencana membuka hutan untuk menanam tanaman yang menghasilkan bioenergi bukanlah solusi baru, tetapi bagian dari pendekatan pembangunan berbasis ekspansi lahan yang telah dikritik selama ini. Pembukaan hutan untuk sawit, tambang, dan proyek ekstraktif lainnya merupakan salah satu penyebab struktural terjadinya krisis lingkungan, termasuk mengurangi kemampuan lanskap untuk menyerap curah hujan ekstrem, memperparah banjir, dan merusak sumber penghidupan masyarakat adat serta masyarakat lokal.
Walhi mengingatkan bahwa kedaulatan energetika harus menjadi prioritas negara, tidak cukup hanya swasembada pangan dan energi. Energetika harus diletakkan dalam kerangka hak, sebab akses terhadap energi yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia. Energi memungkinkan produksi pangan, tempat tinggal layak di berbagai iklim, layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan serta konektivitas.
“Sistem energi harus diletakkan pada pemenuhan kebutuhan hak dasar warga negara bukan pada akumulasi kapital,” ucap Uli.
Walhi Papua, juga menilai kebijakan swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan luas, bukan berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat. Monokultur besar seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua.
“Hal ini sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan,” kata Maikel Peuki.
Maikel menganggap Presiden Prabowo mengabaikan otonomi khusus dan pemerintahan khusus, dengan kewenangan tersendiri menghormati Tanah Papua sebagai bukan tanah kosong—ada pemilik adat yang berhak atas tanah dan hutan adat. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga dianggap belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif (free, prior, and informed consent/FPIC) sebelum mengambil keputusan.
“Kebijakan ini dapat memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu, dan hasil hutan lainnya,” kata Maikel.
Tidak belajar dari bencana ekologis Sumatera
Sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya menilai Presiden Prabowo tidak belajar dari bencana ekologis Sumatera. Deforestasi masif oleh bisnis ekstraktif perkebunan sawit dan kehutanan, telah mengakibatkan 1.059 orang meninggal, 192 orang hilang, dan sekitar 7 ribu orang terluka (data BNPB hingga 17 Desember 2025). Bencana Sumatera juga mendatangkan kerugian ekonomi mencapai Rp. 68,8 triliun dan kehilangan harta benda dan infrastruktur sosial ekonomi.
Mereka menilai pernyataan “Papua harus ditanami” yang dilontarkan Prabowo mencerminkan pendekatan top-down yang menafikan hak menentukan nasib sendiri atas ruang hidup. Dalam hal ini Papua kembali diposisikan sebagai objek kebijakan nasional dan mengabaikan hak masyarakat adat.
Pernyataan tersebut mengandung logika kolonial, yakni negara paling berkuasa menentukan dan mengubah kehidupan sosial rakyat dan lingkungan alam di Tanah Papua, seolah-olah Papua adalah ruang kosong yang menunggu diisi proyek negara.
Asep Komarudin, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia mengatakan, demi ambisi swasembada pangan dan energi, Prabowo menyiapkan bencana ekologis bagi Papua. Untuk memenuhi ambisi Prabowo jutaan hutan alam Papua harus hilang untuk ditanam beras, sawit, tebu dan singkong.
“Prabowo juga mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan Tanah Papua,” kata Asep.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengidentifikasi ada 94 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua dengan luas 1.332.032 hektare. Ironisnya, perkebunan sawit dimaksud hanya dikuasai dan dimiliki segelintir korporasi yang dekat dengan penguasa. Penguasaan tanah skala luas dan penggundulan hutan untuk produksi dan perluasan bisnis energi ini telah menghadirkan masalah sosial ekonomi perampasan tanah, deforestasi dan penghancuran lingkungan.
Di Merauke proyek swasembada pangan dan energi sudah berjalan hampir 2 tahun, yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan perizinan kelayakan usaha yang memadai. Dalam waktu singkat kawasan hutan alam hilang lebih dari 22.680 hektare, masyarakat adat dan Pembela HAM Lingkungan hidup dengan rasa tidak aman.
Proyek tersebut melibatkan ribuan militer, terjadi tekanan dan ancaman oral, fisik dan psikis. Terjadi bencana banjir di daerah sekitar konsesi di Distrik Jagebob, Tanah Miring, Muting dan Eligobel, yang menenggelamkan lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Ditengarai akibat penggundulan hutan untuk perkebunan tebu PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri dan perkebunan kelapa sawit di hulu sungai.
Tigor Hutapea, staf advokasi Yayasan Pusala Bentala Rakyat, mengatakan, dalam skema alih fungsi hutan ini, yang paling diuntungkan adalah korporasi besar perkebunan dan investor, elite politik dan ekonomi yang menikmati rente perizinan. Sebaliknya, masyarakat adat Papua diposisikan sebagai penghalang pembangunan atau penerima “kompensasi”, bukan pemilik sah tanah dan hutan.
“Proses persetujuan sering kali mengabaikan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) yang sejati. Konsultasi dilakukan secara formalitas, tanpa informasi utuh, dalam situasi relasi kuasa yang timpang,” katanya.
Kelompok masyarakat sipil memandang Indonesia selalu mengklaim memiliki komitmen kuat dalam aksi iklim global dengan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Tapi melihat kebijakan dan ambisi Prabowo satu tahun ini hal tersebut terasa sangat berparadoks.
Riset Greenpeace secara konsisten menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama deforestasi, degradasi gambut, dan peningkatan emisi karbon di Indonesia. Ketika Sumatra dan Kalimantan telah mengalami kerusakan masif akibat sawit, Papua kini diarahkan menjadi frontier baru industri yang sama—dengan pola yang nyaris identik.
Greenpeace mencatat, sebagian besar konsesi sawit di Papua berada di kawasan berhutan, termasuk hutan primer dan wilayah bernilai konservasi tinggi. Pembukaan lahan sering dilakukan jauh sebelum kebun benar-benar produktif, meninggalkan kerusakan ekologis yang bersifat permanen.
Jika seluruh emisi dari perubahan tata guna lahan diperhitungkan, bioenergi berbasis sawit justru memperparah krisis iklim, bukan menyelesaikannya. Menyebut sawit sebagai jalan menuju swasembada energi adalah ilusi kebijakan yang mengabaikan biaya lingkungan dan sosial yang ditanggung publik. Ini jelas solusi palsu terhadap krisis iklim dan jadi sumber konflik baru.
Kelompok masyarakat sipil melihat kondisi yang terjadi saat ini seharusnya sudah cukup menyadarkan Prabowo bahwa proyek-proyek ambisinya membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.
Karenanya kelompok masyarakat sipil ini menyatakan sikap agar Prabowo meralat pernyataannya dan segera menghentikan proyek-proyek industri ekstraktif yang menghancurkan hutan Papua. Selain itu, kelompok masyarakat sipil juga meminta proyek serakah-nomics yang menghisap darah rakyat disetop, dan segera melakukan upaya pemulihan hak masyarakat adat dan pemulihan lingkungan hidup.
Ekspansi sawit di Papua tidak miliki dasar ekologi
Sawit Watch bahkan menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana ekspansi perkebunan sawit skala besar di Papua dengan dalih produksi BBM energi alternatif. Rencana yang sejalan dengan target ekstensifikasi lahan 600 ribu hektare pada 2026 dan mandatori B50 ini adalah strategi 'jalan pintas' yang berisiko memicu bencana ekologis, konflik agraria, dan krisis pangan.
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, mengatakan rencana Prabowo ini merupakan kebijakan yang sangat berbahaya, mengancam kelestarian hutan hujan tropis terakhir di Indonesia, dan mengabaikan pelajaran pahit dari krisis lingkungan yang saat ini sedang melanda Sumatera.
“Strategi ekspansi di Papua tidak memiliki dasar ekologis dan tata ruang yang kuat,” katanya.
Analisis Sawit Watch, lanjur Surambo, berdasarkan riset Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) menunjukkan, total potensi lahan sawit yang sesuai dan optimal (Nilai Batas Atas/CAP) di Pulau Papua adalah 290.837,03 hektare. Luas perkebunan sawit eksisting di Papua pada 2022 telah mencapai 290.659,14 hektare.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa luas kebun sawit yang ada ini sudah sangat krusial dan hampir mendekati kapasitas ekosistem (cap) yang ideal. Bahkan, 75.308,04 hektare perkebunan sawit eksisting di Papua sudah berada di wilayah dengan variabel pembatas (VP) seperti hutan primer, kawasan konservasi, KBA, dan habitat burung cenderawasih.
Surambo bilang, rencana ekspansi di Papua dikhawatirkan akan memicu gelombang konflik agraria baru. Data Sawit Watch mencatat setidaknya sudah ada 1.126 konflik di perkebunan sawit di Indonesia, melibatkan 385 perusahaan dan 131 grup.
“Masyarakat adat Papua, dengan hak ulayatnya, akan menjadi korban utama kriminalisasi dan kekerasan dalam skema 'jalan pintas' ekstensifikasi ini,” ujar Surambo.
Jika bercermin pada kejadian di Sumatera, imbuh Surambo, krisis iklim dan bencana ekologis yang terjadi di sana merupakan bukti nyata dari kegagalan tata kelola sawit dan pelanggaran daya dukung lingkungan. Pembukaan lahan baru di Papua sama dengan menghancurkan ekosistem penting bagi Indonesia dan Dunia ini secara permanen.
“Kami menilai pemerintah telah salah mengambil kalkulasi ekonomi dengan memilih ekspansi,” katanya.
Hasil riset Sawit Watch menunjukkan skenario ekspansi sawit tanpa moratorium diproyeksikan menghasilkan output PDB negatif hingga minus Rp30,4 triliun pada 2045, disebabkan oleh membengkaknya biaya sosial, penanganan bencana, dan hilangnya jasa lingkungan.
Sebaliknya, skema moratorium permanen yang disertai peremajaan sawit akyat (replanting) justru akan memberikan output ekonomi yang jauh lebih tinggi, memproyeksikan output PDB positif hingga Rp30,5 triliun dan mampu menyerap 827 ribu orang tenaga kerja hingga 2045.
Untuk itu menghindari bencana ekologis dan konflik agraria, Sawit Watch mendesak Presiden Prabowo untuk, yang pertama, membatalkan rencana ekspansi sawit di Papua dan target 600 ribu hektare. Fokus harus dialihkan dari ekstensifikasi ke intensifikasi melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang masif dan adil, didukung teknologi dan bibit unggul, demi meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan.
Kedua, menerbitkan kembali peraturan presiden (Perpres) tentang moratorium izin sawit baru secara permanen. Perpres dimaksud harus mewajibkan audit menyeluruh terhadap seluruh izin perkebunan sawit, terutama di wilayah variabel pembatas di Sumatera dan Papua, dan menuntaskan persoalan sawit dalam kawasan hutan.
Yang ketiga, perlindungan hak masyarakat adat. Itu dilakukan dengan mengutamakan pengakuan dan penetapan wilayah adat, terutama di Papua, dan menyelesaikan konflik agraria sawit yang sudah ada, sebagai prasyarat mutlak pembangunan.
Surambo menambahkan, bencana ekologis di Sumatera adalah peringatan keras. Rencana ekspansi sawit di Papua, menurutnya adalah bencana yang tertunda.
“Kami mendesak Presiden untuk mendengarkan sains dan suara masyarakat, serta mengambil kebijakan yang benar-benar menjamin keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang,” katanya.


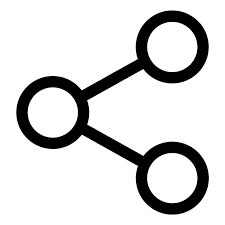 Share
Share

