
LIPUTAN KHUSUS:
Kritik Ditindas, Aksi Iklim Kandas
Penulis : Purwanto Setiadi, JURNALIS
Represi bukan hanya membungkam kritik; ia melemahkan fondasi penting keadilan iklim.
OPINI
Jumat, 05 September 2025
Editor : Yosep Suprayogi
INDONESIA telah menjanjikan pencapaian net-zerro pada 2060. Tapi dengan pencapaian kemajuannya yang lambat, dan ruang demokrasi yang bertambah menyempit setelah tindakan keras yang brutal terhadap demonstrasi besar di seluruh negeri pekan lalu, siapa yang dapat menjamin janji ini bukan sekadar slogan?
Situasi yang menimbulkan pesimisme itu sebetulnya sudah perlahan-lahan terbentuk dalam rentang sepuluh tahun terakhir, melalui proses yang dijustifikasi atas nama reformasi, tapi dalam praktik dicapai dengan mengerdilkan dan melemahkan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif semakin dikuasai kepentingan-kepentingan elite; Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lagi independen, bergantung pada presiden; kepolisian dan institusi peradilan yang dibiarkan korup. Pada saat yang sama, ruang sipil dipersempit melalui pembungkaman aksi-aksi protes dengan kekerasan yang dilakukan polisi, intimidasi dan kriminalisasi aktivis lingkungan, dan restriksi terhadap media.
Yang tak kalah pentingnya, dalam hal itu, adalah semakin terpusatnya dan tertutupnya proses pembuatan kebijakan dan keputusan-keputusan yang terkait dengannya. Berbagai undang-undang mutakhir, misalnya, disusun, dibahas, dan ditetapkan secara sembunyi-sembunyi serta mengabaikan keterlibatan publik secara luas atau tidak ada partisipasi yang bermakna.
Konsekuensi dari situasi tersebut bakal dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Dan tidak ada tempat yang lebih mengkhawatirkan daripada dampaknya di bidang lingkungan hidup. Bidang ini membutuhkan visi dan keadilan jangka panjang--perlu agenda iklim untuk menanggulangi ancaman bencana ekologi, juga mewujudkan keadilan bagi mereka yang terdampak. Semua ini berisiko menghilang dari agenda prioritas pemerintah.

Risiko-risiko yang menghadang terkait dengan hal itu adalah akuntabilitas yang melemah, pembungkaman atas suara-suara dari masyarakat adat dan komunitas lokal, ketidakstabilan kebijakan dan penglihatan yang kelewat berjangka pendek, serta erosi kredibilitas internasional. Semua ini berpeluang besar menimbulkan kontrol yang mengendur terhadap proyek-proyek ekstraktif (pertambangan nikel, food estate, perkebunan kelapa sawit); peminggiran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam keputusan-keputusan terkait dengan lahan, hutan, transisi energi; perencanaan aksi iklim jangka panjang jadi tak penting; dan menguapnya peluang pendanaan iklim.
Bagaimana hutan menghilang dalam skala yang besar akibat pembukaan lahan untuk proyek lumbung pangan (food estate) dan lain-lain adalah contoh yang gamblang. Data Global Forest Review yang dirilis World Resources Institute menunjukkan kontribusi Indonesia dalam total hutan yang hilang di level global pada 2022 mencapai 230 ribu hektare. Ini meningkat setahun kemudian, menjadi 290 ribu hektare. Di Papua Selatan saja, lokasi proyek kebun pangan dan energi raksasa pada era pemerintahan Presiden Prabowo, dalam periode itu hutan yang lenyap mencapai 190 ribu hektare--ini setara dengan tiga kali luas Daerah Khusus Jakarta.
Proyek itu, juga proyek-proyek serupa yang lain, umumnya merampas wilayah hutan dan lahan berbagai masyarakat adat dan komunitas lokal dan menimbulkan kerusakan lingkungan (pembabatan hutan, hilangnya biodiversitas, dan pencemaran). Protes telah timbul di mana-mana. Tapi pemberangusan suara dan upaya penumpasannya melalui intimidasi dan kekerasan dilakukan tak kalah gencarnya.
Perkembangan-perkembangan itu menimbulkan kekhawatiran prospek pendanaan iklim dapat mengering. Perihal pendanaan ini banyak faktor yang berperan sebagai penentu, sebenarnya. Just Energy Transition Partnership, umpamanya, yang sebetulnya terguncang akibat keluarnya Amerika Serikat. Meski demikian, seperti halnya investasi yang selalu menimbang risiko yang berkaitan dengan kondisi politik, sangat boleh jadi represi di dalam negeri bakal menutup celah yang masih mungkin sekalipun.
Tanpa memulihkan akuntabilitas dan demokratisasi dalam kebijakan-kebijakan publik, bahkan pendanaan iklim yang paling dermawan pun akan dihambur-hamburkan pada proyek-proyek yang merusak lingkungan dan membungkam masyarakat yang seharusnya dilindungi. Karenanya, situasi yang merupakan kemunduran signifikan dari periode awal reformasi saat ini harus dilawan.
Agar keadilan iklim dapat diwujudkan, ia harus didukung demokrasi yang sehat: dengan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Semua ini diperlukan agar kebijakan publik yang dibutuhkan tidak harus membentur risiko bertahannya kegiatan-kegiatan ekstraktif dan ketidakadilan yang menyertainya. Aksi iklim yang bertumpu pada otoritarianisme mungkin bisa meluncurkan proyek-proyek raksasa, tapi penyengsaraannya terhadap rakyat, ekosistem, dan kredibilitas tak bakal terelakkan.
Jelas, berdasarkan hal-hal tersebut, tak bisa dinegasikan bahwa menguatkan demokrasi di negara ini, mencegahnya kembali ke era sebelum reformasi atau malah menjadikannya lebih buruk, tak terpisahkan dari agenda aksi iklim. Demokrasi merupakan esensi di dalamnya. Dekarbonisasi tak bakal bisa dilakukan dengan dekrit; ia bakal berhasil hanya melalui demokrasi.
Kini tantangan bagi pemerintah adalah menjawab substansi tuntutan, yang beredar pasca-demonstrasi berdarah pekan lalu, agar pemimpin negara ini memberdayakan warga negara, melindungi mereka yang berjuang membela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta menjamin akuntabilitas dalam setiap tindakannya.


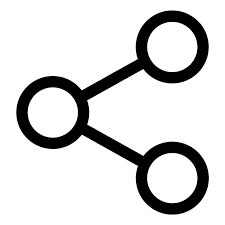 Share
Share

