
LIPUTAN KHUSUS:
Morowali: Nikel Itu Fana, Jangan Abadi Sengsaranya
Penulis : Gilang Helindro
AEER mewanti-wanti, ketidakseimbangan antara eksploitasi dan perlindungan hutan di Morowali akan merugikan secara ekologis dan ekonomi.
Lingkungan
Rabu, 30 Juli 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Laporan terbaru dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengungkap bahwa Total Economic Value (TEV) hutan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mencapai Rp2,81 triliun per tahun. Nilai tersebut 44,61% lebih tinggi dibanding realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2023 sebesar Rp1,94 triliun. Namun, sekitar Rp1,07 triliun per tahun dari nilai ekonomi hutan itu berada di dalam wilayah konsesi tambang nikel dan terancam hilang.
Laporan ini menggunakan pendekatan valuasi total ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012, mencakup manfaat langsung dan tidak langsung, nilai keberadaan, nilai pilihan, dan warisan. Analisis dilakukan dengan data sumber daya alam hutan serta izin pertambangan periode 2023–2025. Teknik overlay menggunakan software ArcGIS serta metode valuasi pasar dan biaya pengganti digunakan untuk mengukur nilai ekonomi dari jasa lingkungan yang tidak tersedia di pasar.
Kabupaten Morowali saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, berkat kehadiran kawasan industri besar seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP). Namun di balik lonjakan ekonomi tersebut, tekanan terhadap ekosistem hutan juga meningkat tajam. Hutan Morowali, yang menyerap lebih dari 1,1 juta ton emisi karbon (CO₂e) per tahun, kini menghadapi ancaman deforestasi yang dapat mengganggu pencapaian target iklim nasional FoLU (Forestry and Other Land Use) Net-Sink 2030.
“Sulawesi adalah wilayah dengan cadangan nikel besar, tapi juga memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Ketidakseimbangan antara eksploitasi dan perlindungan hutan akan merugikan secara ekologis dan ekonomi,” ujar Risky Saputra, peneliti AEER dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 29 Juli 2025.

Data dalam laporan menunjukkan, sejak 2019 hingga 2023, tambang nikel telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan nasional seluas 37.660 hektare, setara dengan emisi 28,7 juta ton CO₂e. Sebanyak 16% dari deforestasi itu, atau sekitar 6.110 hektare, terjadi di Morowali. Saat ini, 35% wilayah Morowali atau 157.935 hektare telah dikonversi menjadi konsesi tambang oleh 70 perusahaan, termasuk 133.256 hektare kawasan hutan dan 97.790 hektare hutan primer yang seharusnya dilindungi.
Meity Ferdiana Pakual, peneliti Universitas Tadulako, menilai valuasi ini menjadi landasan kuat untuk menetapkan moratorium izin baru di hutan primer dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. “Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, tekanan industri nikel akan mempercepat deforestasi dan mengancam target iklim serta keanekaragaman hayati nasional,” ujarnya.
Hutan Morowali juga menjadi rumah bagi spesies endemik dan langka seperti burung Maleo (Macrocephalon maleo), Rangkong Sulawesi (Rhyticeros cassidix), dan Monyet Butung (Macaca ochreata), serta berbagai flora dan fauna yang tercatat dalam basis data Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
Dalam diskusi peluncuran laporan, Akhmad Fauzi, Guru Besar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB, menekankan perlunya perubahan paradigma terhadap sumber daya alam bukan sekadar sebagai faktor produksi, tetapi sebagai modal alam. “Kalau hutan kita ditebang tanpa penguatan nilai tambah, maka aset negara mengalami depresiasi luar biasa,” katanya. Ia juga mendorong pembentukan resource fund dari pemanfaatan SDA untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah melalui pertanian, ekowisata, dan jasa lingkungan.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Subhan Basir dari Bappeda Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa RPJMD 2025–2029 sedang dalam tahap akhir penyusunan dan laporan AEER ini akan dijadikan masukan strategis bagi pimpinan daerah.
AEER juga memberikan tiga rekomendasi utama. Pertama, penghentian izin baru di hutan primer dan kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi, disertai evaluasi menyeluruh terhadap izin yang sudah terbit hingga implementasi Global Biodiversity Framework. Kedua, integrasi potensi keuangan dari perlindungan ekosistem ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional seperti RPJMD, RPJMN, dan SNDC. Ketiga, optimalisasi potensi pendanaan berbasis hasil (result-based finance) dari restorasi lingkungan untuk mendukung target FoLU Net-Sink 2030.
AEER menegaskan, pengabaian terhadap nilai ekologis Morowali tak hanya mengancam ekosistem lokal, tetapi juga memperlemah posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global dan menambah beban mitigasi nasional di masa depan.


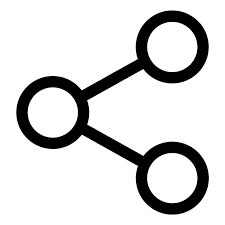 Share
Share

