
LIPUTAN KHUSUS:
Masyarakat Sipil: Sejumlah 'Tak Benar' dalam UU Kehutanan
Penulis : Gilang Helindro
UU Kehutanan baru harus memastikan perlindungan terhadap seluruh hutan yang tersisa, termasuk di kawasan hutan produksi.
Hutan
Selasa, 15 Juli 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi lingkungan, akademisi, dan kelompok adat mendesak DPR RI untuk menerbitkan Undang-Undang Kehutanan baru pengganti UU No. 41 Tahun 1999 yang lebih adil dan melindungi ekosistem hutan. Desakan ini disampaikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (15/7).
Di gedung parlemen ini, kelompok masyarakat sipil mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV tentang revisi UU Kehutanan.
Ketua Auriga, Timer Manurung, mengatakan UU Kehutanan selama ini justru mendorong terjadinya deforestasi. Penyebabnya adalah karena UU Kehutanan hanya fokus pada kawasan hutan, meminggirkan peran penting hutan alam, dan mengabaikan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang hidup dalam hutan.
Menurut Timer, pada saat ini ada sekitar 42 juta hektare--ini sekitar 44 persen--tutupan hutan alam tersisa di Indonesia tanpa perlindungan hukum. Sebanyak 9,7 juta hektare di antaranya berada di luar kawasan hutan atau di Areal Pengunaan Lain (APL), dan 32,7 juta hektare di dalam kawasan hutan produksi yang dibebani izin konsesi, baik itu untuk komoditas hutan produksi, perkebunan sawit, pulp dan lainnya. Karena UU hanya fokus pada kawasan hutan, jumlah hutan alam di APL dan dalam konsesi seolah tak terhitung. “Ini salah kaprah melihat hutan, karena fokusnya kawasan hutan dan melupakan tutupan hutan,” dia menekankan.

Karena itu, ujar Timer, UU Kehutanan tidak boleh lagi melulu soal kawasan hutan. "Tapi fokus pada tutupan hutan,” kata dia. UU baru, kata Timer, harus memastikan perlindungan terhadap seluruh hutan alam tersisa.
Masih ada yang lainnya. UU Kehutanan selama ini memberi kewenangan besar kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Nyaris tidak ada pengurusan hutan yang dilakukan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk masyarakat hutan adat (MHA) serta komunitas lokal. Karena itu, ujarnya, UU Kehutanan yang baru harus membuka ruang pengelolaan. "Jangan melulu diurus pemerintah pusat," kata dia.
Faktanya, hegemoni pusat terlihat pula dalam distribusi aparat kehutanan hingga postur anggarannya. Pada saat ini aparat kehutanan terpusat di Jawa, padahal sebagian besar hutan ada di daerah. Sudah begitu, anggaran yang dialokasikan untuk mengelola kawasan hutan di Jawa lebih besar ketimbang daerah. Misalnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di wilayah Sumatera mengelola 1,4 juta hektare hutan konservasi dengan anggaran pengelolaan per hektar Rp1,6jt. Sementara itu hutan konservasi di Jawa hanya 140 ribu hektare tapi anggaran pengelolaan per hektar mencapai Rp117 juta. Lebih parah lagi anggaran untuk mengelola hutan konservasi di Papua hanya Rp60 ribu. “Ini tidak benar mengelola hutan,” ujarnya.

Perlu UU Kehutanan baru
Dalam konferensi pers daring, kelompok masyarakat sipil juga menyebut UU Kehutanan yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dan gagal memenuhi amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mereka menilai UU 41/1999 masih mempertahankan paradigma kolonial dalam tata kelola hutan yang menempatkan hutan sebagai aset negara untuk dieksploitasi, serta mengabaikan keberadaan masyarakat adat, petani hutan, dan kelestarian lingkungan.
“UU Kehutanan yang lama sudah tidak layak dipertahankan. Perlu diganti dengan regulasi yang menjamin keadilan ekologis dan pengakuan terhadap masyarakat adat,” ujar Anggi Putra Prayoga dari Forest Watch Indonesia.
Koalisi menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam UU 41/1999, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, undang-undang ini disalahartikan dalam penerapan hak menguasai negara. Secara yuridis, UU tersebut telah diubah sebanyak tujuh kali melalui berbagai Perpu, putusan Mahkamah Konstitusi, dan revisi parsial.
Uli Arta Siagian dari WALHI menambahkan bahwa selama ini pengelolaan hutan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi segelintir pihak, sementara akses masyarakat terhadap hutan adat dan perhutanan sosial sangat terbatas. Dari pendampingan WALHI terhadap 1,5 juta hektare wilayah kelola rakyat, hanya 16 persen yang mendapat pengakuan selama sepuluh tahun terakhir.
Sementara itu, Refki Saputra dari Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa 42,6 juta hektare hutan alam masih terancam deforestasi, termasuk di kawasan hutan produksi terbatas dan konversi. Ia menilai moratorium izin hutan yang dikeluarkan melalui instruksi presiden masih lemah dan tidak efektif menghentikan kerusakan.
“UU Kehutanan baru harus menghentikan praktik monetisasi hutan dan memihak pada perlindungan biodiversitas, iklim, serta masyarakat adat,” tegas Refki.
Erwin Dwi Kristianto dari HuMa menekankan pentingnya perubahan paradigma dari rezim pengurusan menjadi rezim pengelolaan. Ia juga mengusulkan agar pengakuan hutan adat masuk dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan pemulihan lahan hutan dilakukan secara sistematis.
Peneliti Madani Berkelanjutan, Sadam Afian Richwanudin, menyoroti bahwa UU 41/1999 tidak mengakomodasi isu perubahan iklim. Ia mendorong UU baru mencantumkan larangan eksploitasi hutan alam oleh industri ekstraktif, termasuk proyek strategis nasional yang sering mendapat keistimewaan.
Sementara itu, Sita Aripurnami dari Women Research Institute menggarisbawahi pentingnya mencantumkan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan dalam UU Kehutanan baru. Ia menyebut perempuan sering terdampak paling besar dalam konflik lahan dan kriminalisasi masyarakat adat.
Patria Rizky dari Kaoem Telapak menambahkan bahwa UU Kehutanan baru harus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan hutan.
Koalisi mengutip Pasal 3 UU 41/1999 yang menyebut tujuan kehutanan adalah untuk kemakmuran rakyat yang adil dan berkelanjutan. Namun evaluasi mereka menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai.
Untuk itu, Koalisi merekomendasikan pembentukan UU Kehutanan yang baru, bukan sekadar revisi parsial. Proses penyusunannya pun harus mengikuti prinsip partisipasi bermakna sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.


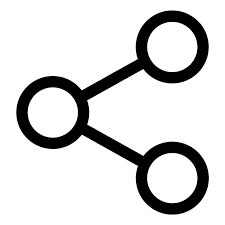 Share
Share

