
LIPUTAN KHUSUS:
Ihwal Hujan Bulan Juli, Greenpeace: Dampak Nyata Krisis Iklim
Penulis : Gilang Helindro
Pemerintah diminta bertindak cepat dan tegas untuk mengurangi emisi dan melindungi rakyat dari dampak krisis iklim yang makin parah.
Iklim
Selasa, 15 Juli 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Curah hujan tinggi yang terus mengguyur sejumlah wilayah Indonesia pada bulan Juli yang seharusnya merupakan puncak musim kemarau mengindikasikan semakin nyatanya ancaman krisis iklim. Wilayah seperti Jabodetabek dan Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat bahkan mengalami banjir, di tengah periode yang seharusnya kering.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kondisi cuaca ekstrem ini dipicu oleh dinamika atmosfer tak biasa. Lemahnya monsun Australia, suhu muka laut yang tetap hangat, serta aktivitas gangguan atmosfer tropis seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby disebut sebagai penyebab hujan deras di musim kemarau.
Greenpeace Indonesia menyatakan, fenomena ini bukan sekadar anomali musiman, melainkan dampak nyata dari krisis iklim akibat pemanasan global. Emisi gas rumah kaca dari energi fosil, deforestasi, dan industri ekstraktif disebut menjadi penyebab utama gangguan sistemik terhadap iklim.
“Kita tidak bisa lagi menormalkan cuaca ekstrem dan musim yang kacau sebagai hal biasa,” kata Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia dalam keterangan resminya dikutip Senin, 14 Juli 2025. “Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk mengurangi emisi dan melindungi rakyat dari dampak krisis iklim yang makin parah.” ungkap Bondan, menambahkan.

Greenpeace menyoroti kebijakan pemerintah yang masih bergantung pada energi fosil. Hingga tahun 2024, Indonesia mencatat rekor produksi batu bara sebesar 836 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya dan jauh melebihi target awal. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah masih merencanakan penambahan PLTU batu bara sebesar 6,3 gigawatt dan pembangkit gas fosil 10,3 gigawatt hingga 2060, yang dinilai akan memperpanjang ketergantungan pada energi kotor.
“Pemerintah harus keluar dari zona nyaman dan menghentikan ketergantungan pada energi fosil,” ujar Bondan. Ia juga menekankan perlunya peta jalan transisi energi yang adil serta pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) yang benar-benar progresif dan tidak menjadi celah bagi solusi palsu seperti co-firing atau gasifikasi batu bara.
Greenpeace mendesak agar krisis iklim menjadi pertimbangan utama dalam seluruh proses perencanaan pembangunan nasional. Tanpa komitmen nyata untuk menurunkan emisi, masyarakat Indonesia akan terus menghadapi dampak seperti gagal panen, krisis air bersih, dan bencana iklim lainnya di masa depan.


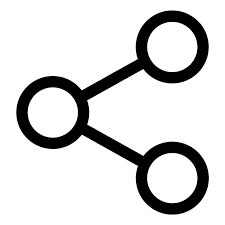 Share
Share

