
LIPUTAN KHUSUS:
Tambang di Pulau Kecil: Perusahaan Datang, Konflik Suku Terbilang
Penulis : Aryo Bhawono
Hadirnya tambang di kepulauan memicu konflik antar suku maupun sub suku. Sebagian menanggung kerusakan lingkungan akibat tambang hingga harus mencari makan di wilayah ulayat suku lainnya.
SOROT
Senin, 14 Juli 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Hadirnya tambang di kepulauan memicu konflik antar suku maupun sub suku. Sebagian menanggung kerusakan lingkungan akibat tambang hingga harus mencari makan di wilayah ulayat suku lainnya. Ironisnya, temuan Betahita menunjukkan, negara bisa datang bukan untuk menengahi, melainkan membela tambang.
Betahita mencatat, klaim dukungan masyarakat berkali-kali disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sewaktu menjawab keberadaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Juni 2025 lalu. Klaim ini pun masih dikatakan ketika pemerintah mempertahankan izin PT Gag Nikel di Pulau Gag dan mencabut izin empat tambang nikel lainnya di Raja Ampat.
Empat perusahaan pemegang izin itu adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP) di Pulau Manuran, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau Batang Pele, dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di Pulau Kawe.
Masalahnya, Betahita menemukan, soal dukungan masyarakat sekitar tak sesepele yang dikatakan Bahlil. Hadirnya tambang hingga dicabutnya lagi izin tambang ini menyisakan konflik di kepulauan yang menjadi surga dunia itu. Pencabutan izin PT KSM misalnya, membawa konflik bagi Suku Kawe. Suku ini merupakan pemilik wilayah kelola adat di Pulau Kawe, lokasi tambang PT KSM, dan Pulau Wayag, yang menjadi ikon pariwisata Raja Ampat.

Warga Suku Kawe di Desa Salio, Jefri Dimalaw, mengakui sukunya menghadapi dilema atas keberadaan hingga pencabutan tambang. Sebagian dari mereka mendukung satu dari empat perusahaan tambang yang dicabut pemerintah, yakni PT KSM. Suku Kawe yang bermukim di Desa Salpele, Waigeo Barat, menolak pencabutan itu hingga melakukan aksi pengusiran turis yang bertandang ke Pulau Wayag.
Mereka yang setuju dengan tambang terlanjur menggantungkan nafkahnya dengan tambang PT KSM. Sebagian dari mereka menerima royalti, bekerja sebagai karyawan, hingga menjual hasil laut kepada perusahaan itu.
 Tangkapan layar keterangan pers menteri terkait pencabutan 4 IUP di Raja Ampat, pada Selasa (10/6/2025). Sumber: Youtube Sekretariat Presiden.
Tangkapan layar keterangan pers menteri terkait pencabutan 4 IUP di Raja Ampat, pada Selasa (10/6/2025). Sumber: Youtube Sekretariat Presiden.
Namun Suku Kawe yang hidup di desa tetangga mereka, Desa Salio, memprotes penutupan lokasi wisata sekaligus mendukung penutupan tambang. Mereka merasa terancam karena dampak tambang berpotensi besar merusak lingkungan. Mereka khawatir tambang akan merusak perairan. Sebagian suku itu menggantungkan pencaharian dari pariwisata ataupun menjadi nelayan.
Mereka pun menggelar protes atas pengusiran wisatawan di Wayag ini.
“Memang ada dilemanya. Sebenarnya beberapa masyarakat adat tidak setuju karena tidak dilibatkan, dan memang Desa Selpele setuju tapi di Salio tidak setuju karena tidak dilibatkan,” ujarnya melalui telepon pada Senin (7/7//2025).
Polemik antar suku Kawe ini belum juga menemui titik temu. Pemalangan Pulau Wayag sejak 10 Juni 2025 lalu belum menemukan penyelesaian. Aksi itu melumpuhkan kunjungan wisata ke Pulau Wayag.
Jefri sendiri merupakan pihak yang tidak setuju dengan aktivitas tambang di Pulau Kawe. Alasan utamanya menolak tambang itu adalah kehadiran perusahaan tambang yang tidak terbuka. Selain itu, ia merasa bahwa tambang berpotensi besar merusak lingkungan wilayah kelola Suku Kawe.
“Jelas ada yang terganggu dengan pemalangan ini. Sekarang homestay di sana tidak ada wisatawan. Saya sendiri yang menjadi pengepul mendapati nelayan tak leluasa mengambil ikan di sekitar Pulau Wayag. Bukan tidak boleh, tapi karena kami menghormati pemalangan itu,” kata dia.
Antropolog Universitas Papua, George Alexander Frans Mentansan, menyebutkan masyarakat adat di Raja Ampat sangat kompleks sehingga tak dapat sembarangan mengklaim dukungan masyarakat atas usaha tambang. Pada kasus Suku Kawe, pemerintah dan perusahaan, entah tak jeli atau sengaja memberikan informasi soal tambang hanya pada sebagian suku itu. Hal ini pun lantas menimbulkan konflik di masyarakat.
Seorang nelayan melintas di perkampungan Pulau Manyaifun, Raja Ampat, Papua Barat daya. Foto: Auriga Nusantara/ Fajar Sandika Negara
Kawe, kata dia merupakan sub suku dari suku asli. dengan wilayah penguasaan mereka Waigeo bagian barat. Setiap suku, termasuk Kawe, telah memiliki struktur adat pengelolaan laut hingga hutan. Apalagi setiap jengkal kawasan di Raja Ampat merupakan Suaka Alam Perairan.
“Jadi mestinya, mekanisme terbuka dilakukan. Setiap suku maupun sub suku memiliki dewan adat, lembaga adat, dan tua-tua adat. Mereka yang mengelola suaka alam perairan,” kata Mentansan.
Pemerintah seharusnya tak memperkeruh suasana dengan klaim dukungan masyarakat jika kehadiran tambang sendiri tak dilakukan secara terbuka. Kondisi ini justru akan memperkeruh konflik.
Suku dan sub suku di Raja Ampat
Ia mengingatkan kompleksnya suku di Raja Ampat tak lepas dari posisi geografisnya. Letak Raja Ampat di depan kepala burung mendudukkannya sebagai penerima suku dan budaya luar sebelum mereka memasuki tanah besar Papua. Pertemuan suku dan budaya luar ini membentuk keragaman suku-suku yang hidup di Raja Ampat.
Penduduk asli Raja Ampat adalah suku Ma’ya, mereka hidup di seluruh empat pulau besar dan sekitar 300 pulau-pulau kecil di kepulauan itu. Empat pulau besar tersebut adalah Waigeo, Misool, Salawati, dan Batanta.
“Pada masa kesultanan Tidore, Suku Biak yang mempersembahkan upeti melalui Raja Ampat dan singgah. Lama kelamaan mereka bermukim dan membentuk suku Beser atau Beteuw,” ucap dia.
Tak hanya dari Biak, suku-suku di bawah Kerajaan Ternate dan Tidore juga singgah hingga bermukim di kepulauan Raja Ampat pada sekitar. Mereka dikenal sebagai suku Umkai.
Selain itu terdapat suku-suku yang lahir karena perkawinan campur seperti Usba, Kafdarun, dan Wardo.
Mereka hidup dan menempati pulau-pulau ratusan tahun sehingga tidak bisa disebut sebagai orang luar, tetapi merupakan bagian suku Raja Ampat. Menurutnya keanekaragaman budaya tinggi ini menyimpan rasa sensitif yang tinggi.
Peraturan Bupati Raja Ampat No 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Suku Dan Sub Suku, Daerah Pengangkatan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menyebutkan terdapat enam suku di kepulauan itu.
Suku-suku tersebut adalah Suku Maya Ambel Worem, Maya Klanafat, Matbat, Betew Kafdarun, Wardo, dan Usha. Masing-masing suku tersebut memiliki beragam sub suku yang hidup tersebar di kepulauan Raja Ampat.
Kawe sendiri merupakan sub suku dari Suku Maya Ambel Worem. Mereka mendiami kawasan menyebutkan desa tempat tinggal mereka berada di Pulau Waigeo bagian barat.
Keterikatan suku-suku asli Raja Ampat dengan kelestarian gugusan pulau dan perairan sudah terbentuk alamiah. Sekitar tahun 1998, survei cepat dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Cenderawasih, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendeteksi keanekaragaman hayati tinggi di Raja Ampat.
Namun kekayaan keanekaragaman hayati ini terancam oleh praktik pencarian ikan dengan bom atau kerap disebut dengan dopis, maupun racun. Praktik ini dilakukan oleh nelayan dari luar Raja Ampat dan tak jarang bekerjasama dengan warga sekitar. Pastinya kerusakan parah justru terdeteksi di wilayah pemukiman.
Pesisir dan koral terlihat jelas di bawah air jernih Pulau Batang Pele. Keindahan ini terancam oleh pertambangan nikel. Foto: Auriga Nusantara/ Fajar Sandika Negara
Pada awal tahun 2000-an organisasi konservasi lingkungan, seperti The Nature Conservancy (TNC) dan Conservation International (CI) melakukan sosialisasi konservasi dan kampanye penghentian perusakan perairan. Mereka menggunakan pendekatan budaya maupun ekonomi yang berjalan cukup efektif.
“Awalnya kegiatan itu dilakukan di Teluk Mayalibit, Distrik Waifoi, tempat itu merupakan kampungnya suku asli, Ambel Maya. Mulai dari situ dilakukan sosialisasi sampai dengan pembentukan wilayah kelola adat hingga ke Misool, Batanta, dan permukiman lain,” kata dia.
Mereka menciptakan mekanisme wilayah kelola adat sesuai dengan wilayah tangkap suku dan sub suku. Hingga saat ini, kata Mentansan, sudah terdapat tujuh hingga delapan wilayah konservasi daerah.
Sekitar 2015-2016 lembaga konservasi tersebut menyudahi aktivitasnya dan menyerahkan segala aset kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Aset tersebut berupa pos pengawasan hingga peralatan.
Pemerintah daerah sendiri mengeluarkan Peraturan Bupati Raja Ampat No 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Ikan, Biota Laut Dan Potensi Sumber Daya Alam Lainnya Di Wilayah Pesisir Laut Dalam Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat. Regulasi ini mengatur soal pengelolaan pemanfaatan laut secara adat dan berkelanjutan.
Meski wilayah kelola terbagi dibagi oleh suku dan sub suku namun secara keseluruhan kawasan Raja Ampat ini saling terkait. Selain dampak kerusakan dapat merembet ke wilayah lain, satu suku atau sub suku yang kawasan kelolanya rusak akibat tambang pasti akan mencari ikan ke wilayah kelola lain.
Waigeo Timur yang terlanjur rusak karena tambang
Warga Kampung Yenbekaki di Waigeo Timur, Zeth Simson Awom, menyebutkan kampungnya mengalami dampak parah atas pertambangan nikel PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Perusahaan itu mulai melakukan survei dan sosialisasi pada 2007. Mereka melakukan pembangunan infrastruktur produksi mulai dari pembongkaran jalan, pembangunan stopel (stock pile/ penampungan), hingga pembangunan base camp menyebabkan kerusakan lingkungan.
 Nelayan Yenbekaki di Waigeo Timur, Raja Ampat, Papua Barat Daya memperbaiki perahunya. Foto: FWI
Nelayan Yenbekaki di Waigeo Timur, Raja Ampat, Papua Barat Daya memperbaiki perahunya. Foto: FWI
Endapan akibat aktivitas itu mengotori karang, daratan, hingga dusun sagu. Kerusakan akibat tambang ini merusak wilayah kelola perairan di kampungnya. Mereka tak lagi dapat mencari ikan dan udang.
Beberapa warga kemudian mencari tangkapan laut lebih jauh di wilayah kelola perairan milik kampung sebelah yang dimiliki oleh suku Betew, keturunan Biak. Hal ini pun menimbulkan konflik karena melanggar wilayah kelola perairan.
“Masalahnya adalah ketika kampung sebelah sedang melakukan sasi dalam rangka pembangunan gereja. Warga kampung yang tidak tahu tapi tetap melaut mendapatkan sanksi adat, sanksi adat Biak,” ucapnya.
Sanksi adat itu biasanya berupa denda langsung. Penjatuhan denda ini sekaligus mencegah pelanggaran sasi tidak lagi terjadi. Masalahnya sasi ini berlangsung cukup lama bisa mencapai lima tahun jika mereka mempersiapkan perhelatan besar, seperti acara atau pengembangan gereja.
Tak hanya soal wilayah tangkap saja yang mengalami kerusakan di Yenbekaki. Lokasi peneluran penyu mengalami kerusakan.
“Sejak 2007-2009 itu terjadi pencemaran hebat, ada aksi demo tiga kali di kampung karena di beberapa tahun penyu berkurang. Peneluran berkurang yang awalnya 8-15 jadi 3 sampai 5. Itu untuk identifikasi penyu belimbing (Dermochelys coriacea),” kata dia.
 Data kerusakan di Waigeo Timur akibat tambang nikel. Data: FWI
Data kerusakan di Waigeo Timur akibat tambang nikel. Data: FWI
Zeth merupakan warga yang terlibat sekaligus ketua Sanggar Seni Budaya Anak Raja Ampat Kreatif (Sarak). Selain menjadi lembaga kebudayaan lokal, lembaga ini aktif dalam upaya konservasi. Salah satunya adalah patroli kawasan peneluran penyu bersama masyarakat adat di Yenbekaki.
Ia menyebutkan terdapat lima jenis penyu di Pulau Waigeo, yakni penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu tempayan (Caretta caretta), penyu hijau (Chelonia mydas), penyu lekang lekang (Lepidochelys olivacea), dan penyu belimbing.
 Pulau Manuram di Raja Ampat, Papua Barat Daya dikupas tambang nikel, foto iambil pada akhir 2023. Foto: FWI.
Pulau Manuram di Raja Ampat, Papua Barat Daya dikupas tambang nikel, foto iambil pada akhir 2023. Foto: FWI.
Konflik tak hanya di Raja Ampat
Dampak konflik setelah hadirnya tambang di kepulauan tak hanya terjadi di Raja Ampat. Data Auriga Nusantara mencatat setidaknya tambang bercokol di 289 pulau kecil di Indonesia dibebani oleh 380 unit izin tambang. Luas total konsesi tambang itu mencapai 1,9 juta hektare.
Peneliti Laut Auriga Nusantara, Parid Ridwanuddin, menyebutkan konsesi tambang tersebut tak hanya meliputi daratan melainkan juga perairan. Pengelolaan adat dan tradisional pesisir berhadapan dengan tambang itu. Padahal selama ini mereka setidaknya ikut terlindungi oleh UU No 27 2007 jo UU 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturan itu melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil beserta kesatuan ekologisnya.
Beberapa pulau kecil banyak memang tidak ditinggali, namun masyarakat di sekitar pulau kecil memanfaatkannya sebagai wilayah kelola adat.
“Jadi itu bukan disebut pulau kosong tetapi menjadi persinggahan ataupun wilayah kelola masyarakat adat di sekitar pulau kecil itu. Wilayah kelola ini bisa merupakan lahan garapan di darat dan perikanan di perairannya,” kata dia.
Ia menyebutkan masyarakat adat ataupun lokal maritim sangat terdampak atas aktivitas tambang tersebut. Pada masyarakat Bajo misalnya kehadiran tambang di pulau kecil sekitar tempat hidupnya nyaris seperti kiamat. Permukiman mereka di pesisir dipenuhi sedimen tambang dan terancam banjir. Sementara wilayah tangkap ikan mereka rusak.
Data pemberitaan Betahita merekam dampak tambang nikel di Pulau Kabaena terhadap orang-orang Bajo di sekitar pulau dengan luas 891 km2 itu. Permukiman Bajau di Baliara, tanjung di sisi barat Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. harus mengecap dampak pertambangan di daratan.
Pesisir Baliara memerah sehabis hujan. Lumpur merah yang mengkontaminasi perairan itu berasal dari tambang nikel. Foto: Satya Bumi
Antropolog Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara, Danial, menyebutkan demam nikel telah berdampak besar pada relasi suku Bajo dengan masyarakat daratan di provinsi kaya nikel. Kasus di Kabaena hanya satu dari sekian banyak dampak tambang terhadap suku Bajo.
Suku itu dikenal sebagai masyarakat adat laut. Mereka menghuni perairan di Sulawesi, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Penjelajahan mereka tak mengenal batas negara, bahkan sampai ke Filipina.
Mereka menghuni pesisir dan membuat permukiman di atas air. Danial menyebutkan masyarakat Bajo memiliki hubungan erat dengan penduduk asli di Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
“Ketika mereka mau menetap dan membangun permukiman di sebuah wilayah, orang Bajo akan meminta izin penduduk asli kawasan atau pulau kecil itu. Di Kabaena, mereka meminta izin kepada suku Moronene yang merupakan suku asli di pulau itu,” kata dia.
Namun dengan relasi semacam ini Bajo duduk sebagai pihak yang tak memiliki hak atas tanah. Tak hanya itu, keberadaan mereka tetap dianggap sebagai tamu di daratan sehingga mereka tak pernah duduk dalam pemerintahan maupun pengambil kebijakan.
 Anak-anak Bajau sedang bermain di pesisir, tepatnya di bawah pemukiman saat air sedang surut di Baliara. Foto: Aryo Bhawono/Betahita.
Anak-anak Bajau sedang bermain di pesisir, tepatnya di bawah pemukiman saat air sedang surut di Baliara. Foto: Aryo Bhawono/Betahita.
Ketika tambang datang, kata Danial,mereka pun tidak memiliki bargaining. Masyarakat yang menerima tambang berunding soal pembebasan tanah. Ironisnya, Bajo yang tinggal di pesisir terkena dampak tapi tak diperhitungkan sama sekali.
Hal ini jamak di pesisir maupun pulau kecil. Misalnya saja di Mandiodo (Konawe Utara) hingga Pasir Putih (Bombana).
“Keberpihakan pemerintah tidak kepada masyarakat Bajo ini terlihat sekali. Bahkan kasus di Pulau Labengki di Konawe Utara, masyarakat Bajo disalahkan karena mencari ikan dengan bom ikan,” ujarnya.
Pulau ini merupakan kawasan wisata. Kasus mencari ikan menggunakan bom memang terjadi, tetapi faktor tambang di seberang Labengki di daerah Boenaga, tak pernah dipermasalahkan. Padahal sepanjang daratan di Boenaga yang menghadap Labengki bukaan tambang menganga di sepanjang pesisir hingga daratan.
Relasi masyarakat Bajo dengan masyarakat adat daratan pun kemudian bergeser, tak jarang masyarakat Bajo harus berpindah karena ruang hidup mereka sudah tak layak lagi. . Danial berpendapat bahwa seharusnya pemerintah mencabut tambang di pesisir dan pulau kecil. Selain amanat undang-undang, pertambangan itu merugikan masyarakat pesisir, terutama masyarakat laut seperti Bajo.
Ancaman kriminalisasi masyarakat pulau kecil penolak tambang
Masyarakat asli di pesisir dan pulau kecil, pun tak lepas dari ancaman konflik hingga kriminalisasi. Kehadiran tambang di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, disambut dengan gelombang penolakan tambang.
Warga Wawonii, Sarmanto, menyebutkan perbedaan pendapat soal kehadiran tambang memang terjadi secara terbuka. Perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan sosial. Namun beberapa konflik urusan tanah ditengarai terkait dengan kepentingan perusahaan.
“Ada dugaan warga yang pro tambang, warga sekitar, mengklaim sebuah lahan yang sudah puluhan tahun digarap dan ditinggali oleh warga yang menolak tambang. Ini jadi konflik tanah antar warga,” kata dia.
 Masyarakat Wawonii memagar lahannya. Pemagaran tersebut dilakukan karena perkebunan jambu mete mereka diterobos perusahaan. Foto: Jatam.
Masyarakat Wawonii memagar lahannya. Pemagaran tersebut dilakukan karena perkebunan jambu mete mereka diterobos perusahaan. Foto: Jatam.
Konflik semacam ini banyak terjadi hingga masuk ke pengadilan.
Sarmanto menyebutkan mayoritas warga sendiri menolak kehadiran tambang karena khawatir akan kerusakan lingkungan imbas dari aktivitas tambang. Beberapa kegiatan perusahaan, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), telah merusak sumber air dan mencemari kawasan perairan.
Warga penolak tambang sendiri menghadapi ancaman kriminalisasi melalui pelaporan polisi. Lebih dari 30 warga harus menghadapi pemeriksaan polisi dengan tuduhan menghalang-halangi usaha pertambangan.
Sarmanto menyebutkan meski warga memenangi gugatan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT GKP di Mahkamah Agung, namun sepanjang masa proses gugatan itulah kriminalisasi terjadi.
Sarmanto menyebutkan aparat cenderung mengabaikan fakta bahwa tambang di pulau kecil sudah dilarang oleh UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dengan mendiamkan aktivitas tambang. Mereka justru memilih menindaklanjuti pelaporan perusahaan, baik itu pidana pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, hingga usaha menghalangi perusahaan.


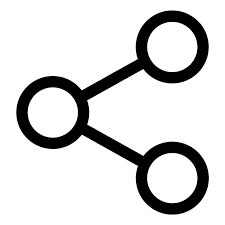 Share
Share

